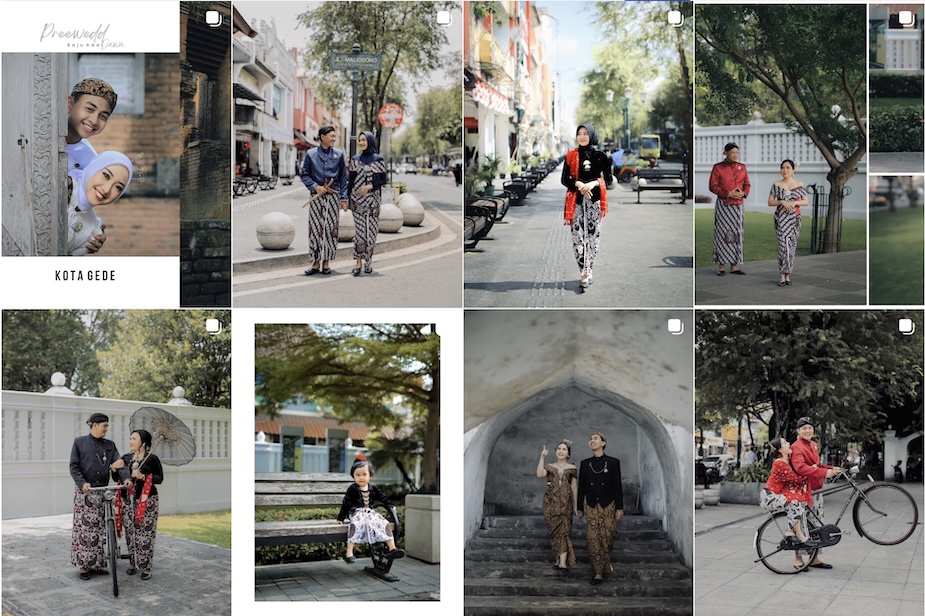Cara baru menulis tentang pertambangan dan penebangan kayu
Siti Maimunah diwawancarai oleh Gerry van Klinken
GvK: Mai, Anda menyelesaikan disertasi PhD Anda di Universitas Passau di Jerman pada 2022. Disertasi tersebut membahas tentang protes lingkungan di sekitar penebangan hutan dan pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah, serta tambang nikel di Sulawesi. Anda menulisnya dengan cara yang sangat tidak biasa – sebagai ‘proyek kehidupan,’ yang melibatkan ‘auto-etnografi.’ Ini terdengar seperti Anda sendiri adalah bagian dari cerita, bukan berdiri di luar dan mengamati seperti dalam tesis ilmu sosial yang ‘normal’. Bisakah Anda menceritakan tentang pendekatan ini dalam menulis tentang penebangan dan pertambangan? Bagaimana Anda mendapatkan ide ini?
SM: Saya menggunakan istilah ‘proyek kehidupan’ karena penelitian saya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan aktivisme. Pada akhir 1990-an saya belajar ilmu pertanian di Universitas Jember di Jawa Timur. Saya tercengang mengetahui: dibutuhkan waktu 300-1000 tahun bagi alam untuk membentuk satu sentimeter tanah subur. Sementara pertambangan menghancurkan tanah itu untuk keuntungan jangka pendek, tanpa memikirkan alam. Saya bergabung dengan Mahasiswa Pecinta Alam (Mapensa). Saya belajar tentang konservasi alam. Kami mulai memprotes rencana taipan Jusuf Merukh (alm.) untuk membuka tambang emas di Taman Nasional Meru Betiri, di perbatasan Kabupaten Jember dan Banyuwangi. Ini adalah rumah terakhir Harimau Jawa.
Ayah saya adalah pedagang emas kecil-kecilan di jalanan Jember. Bagi kami keluarga Madura, emas merupakan simbol eknomi yang tinggi. Pada perayaan Idul Fitri, menggunakan perhiasan emas menunjukkan ‘kesejahteraan’; bahkan jika kami tidak punya uang, setidaknya kami memiliki perhiasan. Tetapi sekarang saya belajar melihat emas dengan cara yang berbeda.
Jusuf Merukh juga terlibat pada tambang emas raksasa Batu Hijau di Sumbawa. Tambang ini membuang lebih dari 100.000 ton limbah tailing ke laut setiap hari.
Saya mulai belajar tentang ‘ekstraktivisme.’ Ini memperluas cakupan dari sekadar bagaimana menjalankan tambang tertentu. Ekstraktivisme adalah pembongkaran sumber daya alam secara besar-besaran untuk diekspor, dengan pengolahan minimal. Hubungan antara tambang di satu tempat dengan kapitalisme global mendorong saya mempertanyakan tentang etika bagaimana kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan alam.
Setelah lulus, saya bergabung dengan Jatam, Jaringan Advokasi Tambang di Indonesia. Saya berkeliling Indonesia untuk belajar dari masyarakat yang terkena dampak pertambangan. Saya mengunjungi tambang emas Jusuf Merukh: tambang Batu Hijau di Sumbawa, dan Minahasa Raya di Sulawesi Utara. Keduanya menggunakan Pembuangan Limbah tailing ke Laut. Rakyat dipercah belah, sebagian pro dan lainnya anti tambang. Namun dampak tambang tersebut melampaui imajinasi saya. Perempuan dan anak-anak menanggung beban terberat. Ini membentuk pemahaman saya dalam menempatkan ‘penelitian’ sebagai bentuk keterlibatan beraktivisme secara etis.
Ekstraktivisme
Pada saat saya tiba di Passau 20 tahun kemudian, saya sudah memiliki gagasan dasar. Pembimbing saya –Martina Padmanabhan dan Rebecca Elmhirst – membantu saya mengembangkannya lebih lanjut. Jelas, subjektivitas dapat masuk ke dalam penelitian kita; bahkan, harus!
Saya mendapat beasiswa penelitian WEGO-ITN dengan topik khusus tentang politik ekologi feminis dan ekstraktivisme – penambangan batubara dan lanskap di Kalimantan Tengah. Saya harus belajar membaca lanskap. Apa yang sudah terjadi di sini dari waktu ke waktu? Dan bukankah orang-orang yang tinggal di sana juga merupakan bagian dari lanskap? Mereka adalah warga negara Indonesia; hubungan sosial juga memungkinkan ekstraktivisme beroperasi melalui kerja mereka.
Ekstraktivisme menyediakan pandangan yang lebih luas. Ia menghubungkan lanskap dengan tubuh manusia di sana. Ada zona di mana kapitalisme berkembang, tidak hanya kepada alam tetapi juga kepada tubuh manusia. Saya mendapati bahwa lanskap yang sama di Kalimantan Tengah di masa lalu telah dan sedang digarap oleh tidak kurang dari empat tambang batubara dan sembilan perusahaan penebangan kayu.
Semua ini merupakan teka-teki, tetapi potongan-potongannya secara bertahap mulai tersusun.
GvK: Apakah proses menumbuhkan kesadaran itu panjang?
SM: Ya. Awalnya saya tidak punya rencana untuk menjadi akademisi, bukan untuk mengambil gelar master dan kemudian PhD.
Selesai memimpin Jatam, saya menjadi koordinator Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim. Saat itulah saya mengetahui tentang hubungan antara iklim dan anak-anak yang tenggelam di lubang tambang batubara yang ditelantarkan, terutama di Kalimantan Timur. Untuk mempelajari hal ini, saya mendaftar program master di Universitas Indonesia dan melakukan tesis saya di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur.
Saya menemukan bahwa kematian anak-anak tersebut tidak satupun berujung pada tindakan hukum. Orang-orang hanya mencatat statistik – kematian terbaru adalah nomor sekian, seperti ritual tanpa akhir yang tidak menjawab apa-apa. Sungguh itu membuat frustasi.
Di mana sebelumnya saya hanya fokus pada dampak tambang saja, kemudian saya mulai mempertanyakan tentang politik yang lebih luas.
Pada 1967, Presiden Suharto memaksakan serangkaian undang-undang ekstraktif – Undang-Undang Investasi Asing, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, dan pada tahun 1968 Undang-Undang Investasi Nasional.
Dan politiknya berlanjut lebih jauh. Pada 1972, ia memperkenalkan Program Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), dan pada 1974 Undang-Undang Perkawinan. Konsekuensi utamanya adalah mendisiplinkan perempuan di ruang domestik, dan memperkuat laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Menjadi perempuan dianggap lebih rendah dan menghadapi beban kerja ganda di keluarga. Bagi saya, ini menjelaskan mengapa tidak ada tindakan hukum ketika anak-anak tenggelam di lubang yang ditelantarkan – para ibu dapat memohon keadilan, tetapi mereka sama sekali tidak dianggap penting.
Ini membawa saya berteman dengan Rahma di Samarinda. Saya masih sering memikirkan dia. Pada Hari Ibu, 22 Desember 2015, putranya, Reyhan, yang berusia 10 tahun, tenggelam di lubang tambang batubara. Keluarga suaminya menyalahkannya karena dianggap tidak mampu merawat anak laki-laki itu; polisi menolak memberikan laporan otopsi kepadanya. Hal ini membuat saya berpikir: Dialah yang melahirkan anak laki-laki ini, tetapi dia tidak memiliki identitas yang meyakinkan polisi untuk bertindak. Kehilangan putra sangat menyakiti dirinya dan suaminya, tetapi penderitaannya berbeda dan lebih dalam.
Namun, saya juga belajar mengenai kekuatannya untuk bertindak. Dia mendatangi sekolah dan melarang murid-murid mendekati lubang tambang. Dia menghubungi perempuan lain yang kehilangan anak dengan cara yang sama. Dia mengunjungi mereka. Akhirnya, dengan bantuan Jatam Kalimantan Timur, dia datang ke Jakarta, bersama suaminya yang dia dorong ikut serta. Mereka bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyerahkan 10.000 tanda tangan petisi seruan penutupan lubang tambang. Rasa kehilangan, telah mengaktifkan perlawanan.
Mollo
GvK: Jadi, apakah ada satu momen tertentu yang membuat Anda berpikir: Ya, ini adalah wawasan baru? Atau apakah itu sebuah pencerahan bertahap?
SM: Bertahap. Tapi ada momen penting. Dan itu berada jauh sebelum Samarinda. Itu terjadi di Mollo, di perbukitan Timor Barat, ketika saya mengenal Aleta Baun. Itui pada 2001 dan 2002. Kala itu dia baru melahirkan anak keduanya. Saya masih bersama Jatam. Ia dibahas di bagian lain dalam edisi Inside Indonesia ini. Dialah yang mengajari saya filosofi masyarakat adat Mollo: Tubuh alam dan tubuh manusia terhubung secara tak terpisahkan. ‘Ketika kita merusak tubuh alam, kita merusak tubuh kita sendiri,’ kata masyarakat Mollo.
Ini berarti mereka juga menolak mengkomodifikasi alam. Mantra mereka berbunyi: ‘Kami hanya menjual apa yang bisa kami buat. Kami tidak menjual apa yang tidak bisa kami buat. Kami tidak bisa menciptakan tanah. Kami tidak bisa menciptakan air. Kami tidak bisa meenciptakan batu.’
Setelah itu saya pergi ke Mollo hampir setiap tahun. Saya akhirnya menulis dua buku. ‘Mollo, Pembangunan dan Perubahan Iklim,’ yang diterbitkan Kompas (2013), membahas tentang bagaimana filosofi adat mereka menantang ideologi Pembangunan, dan tawaran alternatif atas krisis iklim. ‘Penjaga Identitas’ (Teras Mitra, 2017) membahas tentang tenun sebagai identitas Mollo.
Itulah awal kesadaran saya. Kehidupan di kampung menyediakan potongan-potongan pertama dari teka-teki, yang kemudian menyatu dengan potongan-potongan lain seperti kisah penambangan batu bara di Samarinda dan tambang nikel di Sorowako, Sulawesi.
Mollo memiliki ritual yang mereka sebut Naketi. Mereka melakukannya setiap kali mereka perlu berhenti dan berpikir sejenak, ketika menghadapi jalan buntu. Refleksi pribadi atau kolektif untuk berdamai dengan diri sendiri dan dengan alam. Idenya adalah berhenti dan merenung, untuk menghadapi kegagalan, untuk melihat komunitas. Mereka mungkin menyembelih ayam dan membaca mantra. Saya bisa melalukan Naketi pribadi saya sendiri, dalam bentuk yang lebih moderat, untuk mencoba memahami apa yang harus saya lakukan. Saya menyadari bahwa melakukan PhD di luar negeri akan sangat sulit. Tetapi itu akan menciptakan ruang yang saya butuhkan untuk menyelesaikan semua ini.

Dan saya memang menemukan ruang itu di Jerman. Saya mampu mengumpulkan kepingan pengalaman saya. Yang benar-benar membantu saya adalah metode ‘auto-etnografi’. Bang Oji - Noer Fauzi Rachman, salah satu editor buku yang dibahas dalam edisi Inside Indonesia ini - telah memberi tahu saya tentang hal itu sebelumnya, tetapi sekarang semuanya menjadi jelas. Di sinilah saya belajar bahwa di lanskap pertambangan batu bara Murung Raya di Kalimantan Tengah, tubuh manusia dan ruang hidup terhubung, seperti halnya di masa lalu emas terhubung dengan tubuh saya di Jember.
Tubuh saya tidak utuh; bukan entitas yang benar-benar independen. Sebaliknya, ia terhubung dengan alam dalam segala kemungkinan cara. Saya menulis dalam tesis: ‘Tidak mungkin untuk memisahkan dan mengisolasi tubuh individu dari tubuh kolektif, tubuh manusia dari wilayah dan lanskap.’ Menyadari hal ini secara radikal mengubah cara kita menjalani hidup.
Jerman tidak hanya tentang tesis. Saya memulai sekolah ekofeminisme daring secara kolektif di Indonesia, bernama Sekolah Ekofeminisme Ruang Baca Puan. Saat itu pandemi Covid-19, banyak pembatasan di Jerman, jadi banyak waktu luang. Kami membaca naskah Vandana Shiva dan Maria Mies bersama-sama, juga mendengarkan Chimamanda Adichie. Kami akan menyelenggrakan ketujuh kalinya dalam waktu dekat.
Dan pendekatan ‘proyek kehidupan’ kemudian menjadi dasar bagi Mama Aleta Fund yang sekarang saya pimpin di Jakarta. Ini juga merupakan jembatan antara aktivisme dan akademisi. Kami bertujuan menghubungkan kembali kaum muda dengan desa asal mereka. Di sinilah kami menghasilkan buku yang dibahas dalam edisi majalah ini.
GvK: Terima kasih. Saya harap tesis ini akan segera diterbitkan sebagai buku berbahasa Indonesia?
SM: Saya juga berharap begitu – saya sedang mengerjakannya.
Maimunah, Siti. 2022. ‘Reclaiming Tubuh-Tanah Air: a life project on doing feminist political ecology at the capitalist frontier.’ Disertasi PhD, Universitas Passau.
Siti Maimunah akrab dipanggil Mai oleh teman-temannya, mengkoordinasikan Mama Aleta Fund. Sebelumnya, ia menulis di Inside Indonesia tentang Tubuh dan Tanah-Air.