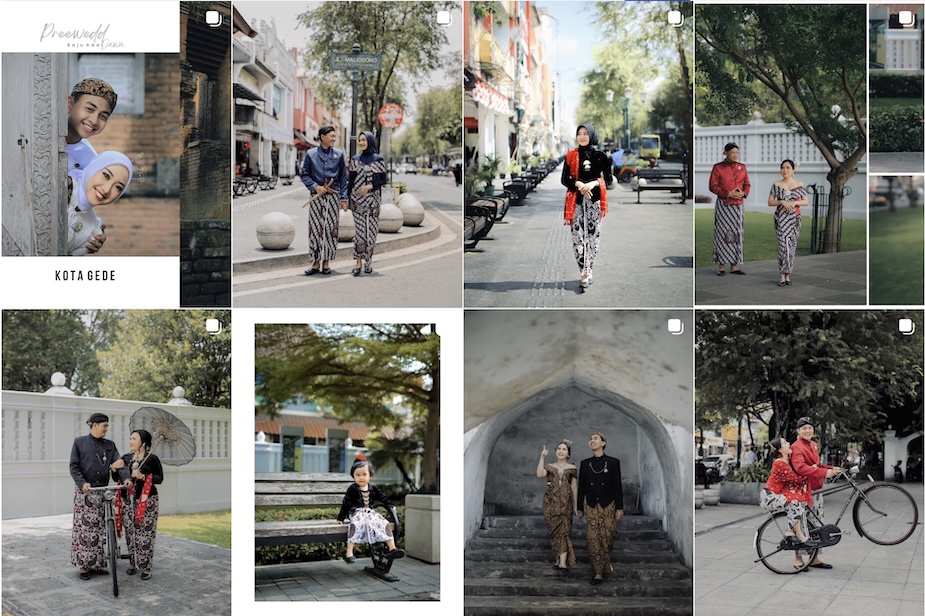Perlawanan batu nama
Batu, pohon, air adalah nama. Kami orang Timur punya nama, dan kami tidak merusak batu nama, air nama, dan pohon nama. Jadi kami sangat mencintai alam, karena batu bukan hanya batu kosong, tetapi batu itu terisi dengan marga. Karena marga orang Timur keluar dari batu, semua marga orang Timur keluar dari air, semua marga orang Timur keluar dari kayu. Sehingga disebut Faut Kanaf, Oe Kanaf, dan Haut Kanaf.
Batu nama adalah identitas orang Mollo. Sebab nama-kedua mereka terkait melalui hubungan leluhur dengan batu. Begitu pula nama Aleta Cornelia Baun yang lebih dikenal sebagai Mama Aleta, perempuan adat Mollo yang memimpin perlawanan untuk menyelamatkan batu nama, Nausus, sejak 1986. Nausus dibongkar oleh perusahaan tambang atas seizin pemerintah demi mengeruk tumpukan batu marmer yang kemudian diangkut dan diekspor ke mancanegara.
Nausus adalah nama sebuah batu yang berada di Desa Fatukoto, tetangga Desa Lelobatan, tanah kelahiran Aleta. Lokasinya di perbukitan Timor Tengah Selatan, ke arah utara dari kota Soe.
Nausus memiliki arti ‘batu yang menyusui [batu lainnya]’. Ia adalah batu keramat yang berada di ujung paling kanan dari dua batu lainnya, yaitu Nanjaf dan Anjaf. Orang Mollo menyebut batu-batu ini sebagai ‘batu nama’, sebab nama marga orang Mollo didapatkan dari kegiatan atau pengalaman hidup di dalam dan di sekitar batu. Pada 1986, pemerintah memberi izin pertambangan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Timor Indah Marmer, PT Karya Asta Alam, PT Soe Indah Marmer, untuk membongkar gunung batu di Mollo dengan keseluruhan luasan 600.000 hektar. Salah satu yang terbesar adalah penambangan batu Nausus yang telah mengakibatkan rusaknya lingkungan dan merugikan warga sekitarnya. Inilah alasan Mama Aleta melawan pemerintah, perusahaan, dan para pendukung proyek tambang.
Aleta Baun, bersama para perempuan Mollo, memimpin perlawanan damai yang terkenal dengan aksi menenun di tapak tambang. Setelah perlawanan sengit pada akhir 2011, empat perusahaan tambang di Mollo berhenti total, dan masyarakat di dua—Tune dan Bon’leo—kembali menguasai tanah adatnya.
Keluarga amaf
Aleta adalah pekerja keras dan sosok yang kaya dengan pengalaman hidup. Dia pernah menjadi pembantu rumah tangga, pengasuh anak, petani, wiraswasta, advokat, istri, ibu rumah tangga, hingga menjadi anggota DPRD Provinsi NTT; dia juga berpengalaman sebagai pekerja lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pengorganisir kampung, yang sempat mengantarkannya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian. Jalan hidup Aleta mungkin berbeda jika dia tidak memilih menjadi pembela Nausus.
Aleta lahir di Lelobatan, Mollo, 59 tahun lalu, dari keluarga amaf, pejabat Kerajaan Netpala. Ayahnya seorang amaf, setara jabatan wakil rakyat di masa sekarang. Tapi jangan membayangkan anak pejabat yang berkelimpahan materi di masa kini. Aleta sejak kecil telah dididik dengan keras, khususnya oleh kakeknya yang tak segan menghukum dengan menali mulutnya kalau dia bolos sekolah.
Alam
Di lingkup keluarga, Aleta dikenal sebagai pemberontak kecil. Melawan bukanlah kata yang asing baginya. Sejak kecil dia dianggap tukang onar di keluarga. Dia punya sebutan khusus ‘si kepala angin’, atau orang yang tak pernah mendengarkan petuah orang lain dan suka berbuat semaunya. Dia suka protes pada ibu tirinya yang pernah menuduhnya mencuri ketimun. Dia juga dianggap tidak sopan karena tidak santun saat bertemu para pejabat kerajaan, tak terkecuali raja. Aleta kecil kerap dihukum karena melanggar aturan keluarga, salah satunya pernah diikat di pohon pisang semalaman.
Aleta suka bermain di dalam hutan bersama teman-temannya. Itulah yang membuatnya mencintai alam. Apalagi wilayah adat orang Mollo yang terkenal dengan kekayaan alamnya seperti pegunungan, hutan, dan mata air yang dianggap sakral. Orang Mollo percaya bahwa tubuh alam seperti tubuh manusia. Filosofi ini tertanam kuat di benak Aleta. ‘Tanah seperti daging, air seperti darah, hutan bagai rambut atau urat nadi, batu seperti tulang. Maka, ketika kita merusak tubuh alam, kita seperti merusak tubuh sendiri,’ ujar Aleta menyampaikan filosofi orang Mollo tentang hubungan alam dan manusia.
Aleta dan para pemimpin adat Mollo yang masih setia pada adat memimpin perjuangan menyelamatkan batu Nausus. Kepemimpinan Aleta membuat perempuan Mollo menjadi barisan terdepan dalam menghentikan pertambangan melalui aksi-aksi damai, termasuk pendudukan tapak tambang dengan menenun hingga berhasil menghentikan operasi tambang. Ia menghidupkan lagi tutur pelambang adat yang menegaskan bahwa tanah, batu, pohon, dan air yang dihormati dalam tradisi mereka memiliki nama-nama marga di antaranya batu sebagai batu kanaf (batu nama), serta air adalah oekanaf (air nama), menandakan keterikatan spiritual yang mendalam antara alam dan komunitas.
Selain memimpin aksi-aksi besar, Aleta juga menjelma sebagai simbol perubahan peran perempuan dalam gerakan sosial, menerabas batas-batas yang selama ini mengekang perempuan dalam ruang-ruang domestik. Pendekatan yang diusung Aleta sejalan dengan pemikiran Nancy Fraser (1998), terutama soal pentingnya menjembatani antara politik pengakuan dengan politik redistribusi. Dalam artikel ceramahnya yang berjudul ‘Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, Participation,’ Fraser berkata bahwa dalam dunia dewasa ini, tuntutan keadilan terbelah dua jenis: tuntutan demi pembagian sumber daya, dan tuntutan demi pengakuan perbedaan budaya. Dalam hal ini, pembelahan tersebut akan berarti bahwa orang bisa berjuang untuk menyelematkan Nausus karena pembagian sumber daya lewat ekstraktivisme marmer tidak adil, atau karena gunung ini memiliki nilai kultural bagi kelompok tertentu, tetapi tidak didorong dua-duanya sekaligus. Justru itu yang harus berubah, kata Fraser. Daripada itu, Fraser menegaskan bahwa keadilan sosial tidak bisa hanya berbicara soal pembagian sumber daya (redistribusi) atau pengakuan identitas semata, tapi harus memadukan keduanya dalam satu kerangka yang utuh.
Kerangka ini utamanya berupaya memahami hubungan antara kelas dan status, juga antara ketidakadilan dan penyangkalan, dalam masyarakat kontemporer. Pendekatan yang memadai harus mampu menangkap kompleksitas hubungan ini—bagaimana status bisa berbeda seturut diferensiasi kelas, dan bagaimana keduanya saling memengaruhi. Pendekatan tersebut juga harus mengakui bahwa ketidakadilan dan penyangkalan punya bentuk berbeda, tapi dalam praktiknya keduanya kerap saling terkait.
Perempuan
Aleta juga memperlihatkan bahwa perjuangan hak-hak atas tanah tidak bisa dipisahkan dari pengakuan eksistensi perempuan dan penghormatan terhadap leluhur serta alam. Pandangan ini jelas sejalan dengan pemikiran para ekofeminis yang juga berakar pada kearifan budaya. Namun, berbeda dengan para ekofeminis kulit putih yang lebih banyak menekankan hubungan universal antara perempuan dan alam, Carol Adams— dalam bukunya Ecofeminism and the Sacred (1993)—mengajak kita untuk melihat keanekaragaman budaya dan agama sebagai kenyataan yang harus dipertimbangkan sekaligus sebagai kekuatan pengubah pada masyarakat dengan pengalaman terjajah di masa lalu. Inti kritiknya adalah bahwa hubungan antara perempuan dan alam bukanlah sesuatu yang tunggal; ia berbeda-beda, tergantung pada konteks budaya dan sejarahnya. Dalam banyak kasus, perjuangan perempuan justru menjadi kuat karena menghidupkan kembali simbol-simbol dari tradisi masyarakat mereka sendiri. Hal ini tercermin dalam aksi-aksi dan ritual adat orang Mollo yang berhasil menghentikan pertambangan di wilayah mereka, termasuk batu Naitapan yang sempat ditambang.

Pada 2005, Aleta bersama para pemimpin adat bersepakat mendirikan organisasi Attaimamus (OAT), yang mengusung misi menyelamatkan wilayah adat Mollo, Amanuban, dan Amanatun. Lewat organisasi ini, perjuangan Aleta bisa meluas, tidak hanya menjaga, tapi juga memulihkan alam. Sepanjang 2009–2014, ia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi NTT. Dorongan untuk memasuki dunia politik dan menjadi anggota parlemen datang juga dari perannya sebagai pemimpin di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang saat itu mendorong para pemimpin adat untuk masuk partai politik dan parlemen. Di sana, Aleta membuktikan bahwa perempuan adat tidak hanya mampu memimpin aksi di lapangan, tetapi bisa juga bisa memperjuangkan hak-hak mereka dan hak-hak masyarakat adat secara umum di ruang-ruang pengambilan keputusan kebijakan publik. Jabatan di DPRD memberinya ruang yang lebih besar untuk memperjuangkan isu-isu agraria dan lingkungan, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam di NTT. Aleta aktif mendorong kebijakan yang lebih pro-lingkungan dan mendukung hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Ia juga terus menentang ekspansi industri tambang dan perkebunan yang dianggap merusak ekosistem serta kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut. Perjuangannya pun meluas, mencakup hak-hak perempuan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Peran dan perjuangan Aleta Baun dalam melawan perusakan alam tak luput dari perhatian publik, baik di dalam maupun dunia internasional. Ketekunan dan keberaniannya membela hak-hak masyarakat adat dan melindungi lingkungan diganjar berbagai penghargaan: Saparinah Sadli Award (2007), Goldman Environmental Prize (2013), Flobamora Award (2014), Yap Thiam Hien Award (2016), dan Lifetime Achievement Award (2024) dari presiden Indonesia.
Tantangan Baru
Ancaman tambang memang belum sepenuhnya hilang dari wilayah Mollo, tapi ada tantangan lain yang tak kalah genting: bagaimana memastikan tanah-tanah adat tetap dikuasai oleh orang Mollo sendiri. Menjawab tantangan ini, Aleta dan komunitasnya mulai memetakan wilayah hutan tradisional mereka; ini bukan sekadar soal batas wilayah, tapi upaya melindungi tanah adat dan mempertahankan sumberdaya alam dari laju eksploitasi sumberdaya alam dan perusakan lingkungan yang makin hari makin ugal-ugalan.
Bersama masyarakat adat, Mama Aleta juga terus kembali melakukan konservasi di lokasi-lokasi bekas tambang. Mereka menanam kembali pohon-pohon, menjaga air, dan, yang tak kalah penting, menguatkan kembali kelompok-kelompok perempuan dan laki-laki yang selama ini menjadi tulang punggung perjuangan mempertahankan kampung. Mereka juga menggiatkan pembuatan tenun-tenun tradisional, bukan hanya untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa alam adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan perempuan. Bagi mereka, menenun merupakan bentuk perlawanan yang lembut tapi kuat.
Pemimpin
Namun, perjuangan ini bukannya tanpa tantangan. Salah satu persoalan yang paling memusingkan Mama Aleta adalah ihwal regenerasi kepemimpinan perempuan. ‘Bagaimana kepemimpinan diteruskan dari apa yang saya lakukan, tidak harus seratus persen dipindahkan ke orang, tapi ada orang yang muncul sebagai pemimpin yang bisa melanjutkan,’ ujar Aleta.
Aleta memahami ada dua jenis pemimpin. Yang pertama adalah mereka yang memang lahir dengan karunia atau karisma kepemimpinan—mereka ini bisa muncul secara alami, apalagi di tengah situasi krisis. Yang kedua adalah mereka yang menjadi pemimpin karena proses: didorong, dibimbing, dan ditempa melalui pengalaman. Jenis kedua inilah yang butuh waktu lebih panjang dan pendampingan hingga siap memimpin.
Tapi bagaimana dengan perempuan? Kebanyakan perempuan tidak punya cukup ruang apalagi kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin. Mereka kerap terjerat dalam kerja-kerja domestik yang menyita hampir seluruh tenaga dan perhatian. Aleta mengusulkan sebuah upaya yang disengaja dan terencana untuk membantu kaum perempuan menyiapkan diri menjadi pemimpin.
‘Itu harus dilakukan dengan persetujuan dan kesadaran. Calon pemimpin harus menyediakan waktunya untuk belajar dari mereka yang berpengalaman, seperti saya. Dia harus mengikuti saya. Ilmu saya bisa dipelajari saat saya bicara dan berkomunikasi dengan orang. Ilmu pengetahuan itu akan lahir setiap saat bertemu dengan orang, karena itu ada momennya. Itu ucapan yang dia dapat sendiri dan saya mulai ajarkan. Tetapi kalau dia mengikuti hanya ketika dia memiliki waktu, ya pasti saya gagal,’ ujar Aleta.