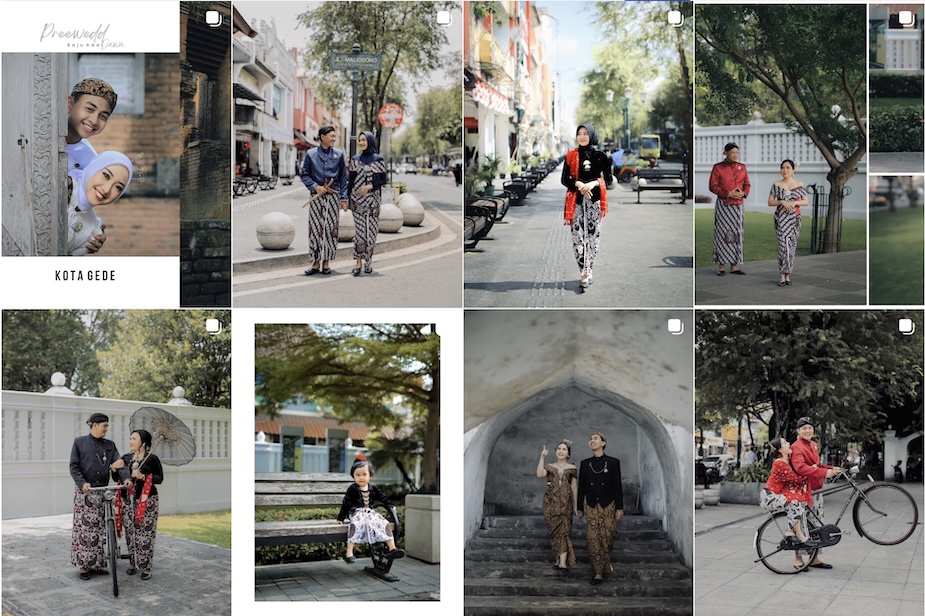12 Tahun di penjara dan jejak Gerwani
Pada suatu sore di tahun 1965, Manismar duduk di sel penjara yang remang-remang di Solok, Sumatera Barat sambil memeluk erat bayinya. Wajahnya memar, kukunya gelap dengan darah. Beberapa jam sebelumnya, dia disiksa oleh interogator polisi untuk mengaku tahu upaya kudeta di Jakarta, kota yang jauh dari kampung halamannya.
Manis, sapaan akrabnya, sekarang berusia 91 tahun. Ia adalah satu dari puluhan ribu perempuan Indonesia yang ditahan tanpa pengadilan pada masa pembantaian anti-komunis tahun 1965-1966 oleh Suharto. Bayinya berusia sembilan bulan bernama Elen ikut ditahan bersamanya. Manis menghabiskan 12 tahun di balik jeruji besi sembari merawat dan membesarkan sang anak.
Pada masa awal penahanan, Manis disiksa oleh Sersan Mayor Baharudin Daulay di kamp tahanan Simpang Rumbio, bekas rumah sakit tentara. Kukunya hancur diinjak kaki meja. Kepalanya dibenturkan ke dinding. Penjaga meneriakinya sebagai mata-mata komunis, pengkhianat dan wanita yang tidak memiliki hak untuk hidup. Seorang petugas lainnya mengacungkan pistol ke kepalanya, mengatakan bahwa hidup Manis bernilai kurang dari seekor ayam.
‘Berharga seekor ayam daripada nyawa kamu,’ katanya.
Dalam satu saat putus asa, bayinya mengalami gangguan pernafasan karena suhu dingin dan lembab di penjara. Manis memohon agar bisa membawa anaknya ke dokter. Seorang sipir yang merasa iba pun mengantarnya. Manis kemudian menjual cincin satu-satunya peninggalan sang ibu untuk membeli obat. Dokter yang memeriksa menawarkan bantuan untuk merawat Elen selagi Manis ditahan, namun Manis menolak.
‘Tapi saya tidak bisa jauh dari anak saya,’ ucap Manis. Setelah pengobatan, Elen berangsur pulih hari demi hari dan kembali ke pelukannya.
Tahanan lain, yang kebanyakan merupakan teman sejawat Manis di Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), organisasi perempuan progresif yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), turut bergiliran menjaga Elen. Mereka saling melindungi satu sama lain, berbagi sedikit makanan kiriman keluarga meski seringkali tak cukup untuk diri sendiri, hingga menyanyikan lagu-lagu anak untuk menidurkan Elen sekaligus menyamarkan jerit tahanan lain yang tengah diinterogasi.
Meski tak menderita sendirian, ada hari di mana duka Manis terasa seribu kali lebih pedih. Pada suatu malam di tahun 1966, rombongan polisi dari kantor lain datang membawa kabar tentang suaminya, Zulkifli Husain, telah dieksekusi mati bersama lima orang lain. Kejahatannya? Berafiliasi dengan Pemuda Rakyat, organisasi yang juga berafiliasi dengan PKI. Hingga hari ini, Manis tak pernah tahu di mana makam suaminya. Tidak ada nisan, tidak ada kejelasan. Hanya duka yang panjang.
Manis juga menuturkan kisah Lasmi, seorang guru taman kanak-kanak (TK) muda dari Sijunjung, Sumatera Barat. Ia merupakan tahanan yang diperkosa petugas lapas berkali-kali. Hingga suatu malam dengan tatapan kosong, Lasmi berpamitan dengan kawan-kawan satu selnya. Lasmi tak pernah terlihat lagi.
‘Dia bilang dia tidak tahan, kemudian pergi,’ lirih Manis menceritakan.
Setelah 12 tahun penahanan sewenang-wenang, pada tahun 1977 Manis resmi bebas dalam amnesti massal. Ia memilih pulang ke kampung halaman, membawa Elen yang mulai beranjak remaja.
Tidak seperti banyak mantan tahanan politik, warga kampung menerima kepulangan Manis tanpa stigma. Tak ada wajib lapor dan pengucilan untuknya. Tetangganya mengingat Manis sebagai sosok berjasa yang pernah mengajar orang-orang tua membaca seraya menjalankan sekolah taman kanak-kanak.
Meski telah kehilangan segalanya; suami, masa muda, dan hak-hak sebagai warga negara, Manis menolak menyerah. Ia melanjutkan hidupnya dalam kesederhanaan. Manis menyimpan semua nama, wajah, dan kisah rekan-rekannya yang hilang di dalam kepala dan sanubarinya. Pada banyak hal, ingatan adalah satu-satunya bentuk keadilan yang bisa ia rawat.
Manismar dan kiprahnya di Gerwani
Lahir pada tahun 1934 di Padang Tinggi, Agam, Sumatera Barat, Manis adalah anak ketujuh dari dua belas bersaudara dan anak perempuan pertama dalam keluarga. Ayah Manis ialah seorang kiai konservatif yang merantau dari Malaysia, sedangkan ibunya mengurus rumah tangga. Sejak kecil Manis merasa mendapat perlakuan berbeda karena terlahir sebagai seorang perempuan.
Manis tumbuh menyaksikan saudara-saudaranya berangkat ke sekolah sementara ia dilarang oleh sang Ayah. Manis hanya diperintah untuk memasak dan belajar agama. Namun tekad Manis untuk sekolah tak pernah surut. Setiap hari ia berjalan kaki sejauh 10 kilometer demi menamatkan sekolah dasar. Ini adalah pemberontakan pertamanya.
Manis terus berjuang melawan norma-norma patriarki yang mengakar di keluarga dan lingkungan. Dengan dukungan rahasia ibunya, pada tahun 1953, Manis bergabung dengan Nasyiatul Aisyiyah, sebuah kelompok perempuan Muslim di bawah naungan Muhammadiyah. Ayah Manis sempat dengan tegas melarang meski akhirnya luluh setelah istri dan anak-anak lainnya membujuk.
Berangkat dari Nasyiatul Aisyiyah, Manis menikmati proses pencarian jati dirinya. Ia pun tersadar bahwa perempuan tidak hanya bisa patuh dan diam. Pada 1955, Manis kemudian melebarkan sayap aktivismenya dengan bergabung Gerwani.
Di kampung halaman Manis di Ladang Laweh, Gerwani tidak dipandang organisasi ekstrem, seperti yang dipropagandakan rezim Orde Baru. Gerwani dikenal baik atas program-programnya yang memberdayakan perempuan. Melalui Gerwani, Manis berjejaring dengan sesama perempuan lintas latar termasuk dengan sejumlah istri tokoh masyarakat yang juga anggota.
Kegigihan dan keaktifan Manis untuk menghidupkan Gerwani serta kedekatannya dengan masyarakat, membuat rekan anggota lain mempercayakannya untuk menjadi pengurus Gerwani Kabupaten Solok.
Karya Manis di Gerwani berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari perempuan pedesaan. Manis membantu seorang ibu agar bisa membaca label obat, mendampingi seorang istri mengatur keuangan keluarga, serta menolong sebuah keluarga agar tidak lagi kelaparan.
Pengabdian Manis tidak berhenti pada urusan perempuan dan keluarga. Ia mulai bersentuhan dengan isu-isu politik yang lebih luas. Pada 1957, Sumatera Barat menjadi salah satu pusat pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)—sebuah gerakan militer dan sipil yang menentang Pemerintah Pusat dengan alasan ketimpangan pembangunan dan dominasi Jawa.
Di tengah kondisi politik dalam negeri yang genting, Manis mengambil sikap untuk mendukung Pemerintah Pusat. Ia memimpin demonstrasi ribuan massa di Solok untuk menolak PRRI. Dengan lantang ia menyerukan dukungannya kepada Presiden Sukarno dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Atas aksinya tersebut, Manis ditangkap dan ditahan oleh polisi selama satu tahun di penjara Muara, Padang. Meski demikian ia tidak pernah menyesal dan merasa bersalah. Baginya menolak pemberontakan bukanlah suatu kriminal.
Hari-hari di dalam tahanan Manis jalani dengan berpegang pada satu prinsip. Ia menolak perlakuan layaknya narapidana dan mengandalkan dukungan dari keluarganya untuk bertahan. Meski pahit, pengalaman itu justru menguatkan keyakinannya bahwa ia berada di jalur yang benar.
‘Saya enggak mau makanan tahanan itu. Saya kalau dikasih, saya enggak biasa makan ini. Saya bukan orang narapidana. Ini saya yang ditahan. Dalam perkara itu saya terperkara lagi,’ tegas Manis.
Setelah bebas dari tahanan Manis kembali aktif di Gerwani. Manis menjadi delegasi Gerwani Sumatera Barat dalam pertemuan internasional organisasi perempuan di Tiongkok pada tahun 1960. Di sana ia bertukar pengalaman dengan perempuan dari berbagai negara dan menyuarakan kondisi perempuan Indonesia; soal pernikahan usia dini, kekerasan rumah tangga, dan keterbatasan akses pendidikan.
Sekembalinya ke Solok, Manis mendirikan taman kanak-kanak dan semakin fokus dalam advokasi sosial. Gerwani di Sumatera Barat pada masa itu berkembang pesat, dan ia termasuk salah satu tokoh penting dalam pembangunan gerakan perempuan di daerahnya.
Bagi Manis, meskipun banyak kebohongan yang disebarkan dalam propaganda Orde Baru, Gerwani bukan sekadar organisasi, melainkan ruang untuk mewujudkan kehidupan yang lebih adil bagi perempuan di sekitarnya melalui kerja nyata yang berakar pada kebutuhan domestik sehari-hari.
Pengalaman Manis menjadi bukti bagaimana perempuan mengalami viktimisasi ganda dan harus menanggung penderitaan berlapis atas peristiwa 1965-1966. Sebagai seorang istri yang suaminya dibunuh, seorang Ibu yang anaknya menghabiskan masa kecil di penjara, serta sebagai pribadi yang menghadapi kekejaman luar biasa. Atas segala ketidakadilan yang ia tanggung, Manis terus menunjukkan sikap teguh dan keberanian. Meminjam kalimat Pramoedya Ananta Toer, Manis telah melawan, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.
Sekar Ayu asisten peneliti di Pusat Kajian Kewargaan dan Hak Asasi Manusia, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta.