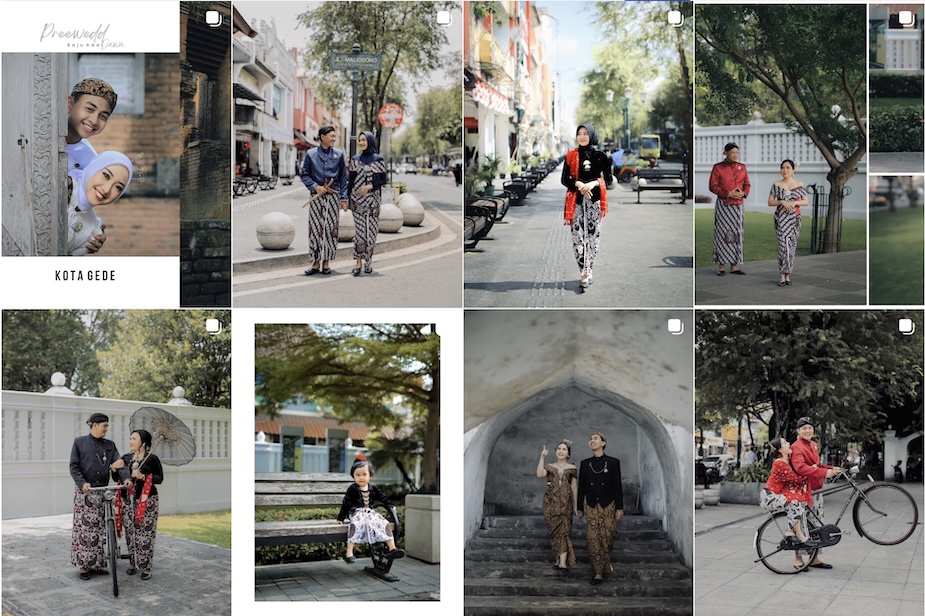Kondisi arsip yang buruk menyebabkan identifikasi korban, pengalaman dan kebutuhan mereka menjadi sangat sulit
Pada 12 Januari 2023, sebuah tim yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo saat itu, mengeluarkan pernyataan beserta sejumlah rekomendasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dibentuk pada tahun 2022, Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) memiliki mandat untuk menyediakan jalur non-yudisial guna mencapai kebenaran, pengakuan, dan pemulihan bagi para korban pelanggaran berat, termasuk pembantaian anti-komunis tahun 1965–1966.
Tim tersebut mengajukan sebelas rekomendasi kepada pemerintah; dari jumlah tersebut, tujuh rekomendasi dinilai sangat sulit untuk dilaksanakan. Rekomendasi kedua terkait dengan penulisan kembali sejarah; rekomendasi ketiga, kelima, dan keenam berkaitan dengan pemulihan hak-hak korban; sedangkan rekomendasi keempat dan ketujuh fokus pada pengumpulan data tentang korban serta pemberian bantuan kepada mereka. Tantangan utama dalam melaksanakan tujuh rekomendasi ini adalah kurangnya data yang dapat diandalkan mengenai identitas, pengalaman, dan kebutuhan para korban. Kesenjangan data ini muncul karena praktik pengarsipan yang buruk terhadap dokumen dan bahan penting milik korban dan penyintas di Indonesia.
Pencarian kebenaran
Mengungkap data tentang genosida 1965–1966 bukanlah hal yang mudah. Peristiwa tersebut terjadi enam puluh tahun yang lalu. Sebagian besar pelaku dan korban telah meninggal, dan ingatan para penyintas pun semakin memudar. Selain itu, trauma yang tersisa, penganiayaan yang berlanjut, dan stigma sosial masih terus memengaruhi korban dan keluarga mereka hingga saat ini.
Ketiadaan data bukan berarti tidak ada upaya untuk mendokumentasikan kebenaran atau pengalaman para korban. Pada tahun 2014, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat pada periode 1965–1966. Dengan menggunakan tujuh wilayah sebagai studi kasus, penyelidikan ini menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan terhadap ribuan warga sipil. Meskipun temuan ini merupakan bagian dari penyelidikan pro justitia (yang terpisah dari penyelidikan pidana), hingga kini Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti laporan tersebut.
Sejak awal Reformasi pada 1998, masyarakat sipil telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mencari kebenaran melalui pendokumentasian pengalaman korban dan upaya rekonsiliasi terkait genosida 1965. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari kegiatan berbasis akar rumput atau komunitas, yang terutama berfokus pada dokumentasi, ekskavasi, memorialisasi, peringatan, rekonsiliasi, serta penyelenggaraan seminar publik. Organisasi lokal dan nasional telah bekerja sama dengan korban dan komunitas akar rumput untuk mengumpulkan banyak kesaksian serta dokumen penting, termasuk surat-surat, karya kreatif, dan barang-barang milik korban. Di beberapa daerah, inisiatif dokumentasi dan pengarsipan ini telah dilakukan oleh LSM seperti Syarikat di Jawa Tengah dan Yogyakarta; SKP HAM Palu (Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Palu) bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mengumpulkan data korban bagi program reparasi lokal; YAPHI (Yayasan Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia) dan Sekber 65 (Sekretariat Bersama ’65) di Solo dan sekitarnya; serta FOPERHAM (Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia) di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
Di tingkat nasional, LSM seperti KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan), ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), dan AJAR (Asia Justice and Rights) telah mengumpulkan kesaksian korban, dokumen pengadilan, laporan media, dan catatan komunitas untuk memastikan bukti pelanggaran tidak hilang dari sejarah. Organisasi-organisasi ini sebelumnya juga berupaya mengoordinasikan dokumentasi melalui jaringan bersama, seperti Jardokber (Jaringan Dokumentasi Bersama). Koalisi masyarakat sipil yang lebih besar, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), berfungsi sebagai forum koordinasi yang lebih luas di mana inisiatif pencarian kebenaran dan rekonsiliasi dilakukan secara nasional. Selain itu, terdapat juga ISSI (Institut Sejarah Sosial Indonesia) yang berbasis di Jakarta, yang pada awal 2000-an mengumpulkan sejumlah besar wawancara terekam dengan banyak korban peristiwa 1965.
Elemen penting lain dari kerja masyarakat sipil ini adalah kelompok-kelompok korban, yang telah dilibatkan oleh LSM dalam sebagian besar inisiatif mereka. Sejak tahun 2000, kelompok penyintas ini secara aktif mendokumentasikan kisah mereka sendiri dan ikut serta dalam upaya pencarian kebenaran serta rekonsiliasi. Masa ‘pembukaan’ tepat setelah jatuhnya Suharto pada 1998 memberi ruang politik bagi korban pelanggaran HAM masa lalu—termasuk pembantaian anti-komunis 1965–1966—untuk membentuk berbagai asosiasi. Organisasi korban seperti YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965), Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru), LPKP 65 (Lembaga Penelitian Korban Pembunuhan 1965), LPK 65 (Lembaga Pembela Korban 1965), LPRKROB (Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban), KKP HAM 65 (Komite Aksi Korban Pelanggaran Hak Asazi Manusia 1965), IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia), serta para korban individual, membentuk berbagai inisiatif pengumpulan kesaksian bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil lain, termasuk aktivis HAM, peneliti, akademisi, guru, dan tokoh masyarakat, untuk mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi pada 1965–1966.
Koleksi terancam punah
Upaya yang dilakukan oleh kelompok penyintas dan organisasi pendukung ini terbukti sangat berhasil; terutama pada dekade pertama setelah 1998, kelompok-kelompok ini berhasil mengumpulkan sejumlah besar kesaksian korban, surat dan catatan, buku, foto, karya seni seperti lukisan atau sketsa, serta artefak. Masalahnya adalah, meskipun setiap kelompok telah mengumpulkan banyak data, jarang ada yang melakukan katalogisasi atau pengarsipan, dan sangat sedikit yang memiliki sistem untuk penyimpanan jangka panjang. Dalam banyak kasus, bahan-bahan tersebut juga disimpan secara berantakan dan tidak terorganisir dengan baik, sehingga menyulitkan akses.

Bagi sebagian besar organisasi ini, termasuk KOMNAS HAM, pendekatan terhadap dokumentasi lebih fokus pada pengumpulan, bukan penyimpanan. Jarang ada kelompok yang membuat ketentuan untuk cara menyimpan dan merawat bahan-bahan mereka. Sebagian besar tidak memiliki sarana untuk membangun sistem pengarsipan yang baik agar catatan mereka tetap terjaga dan dapat diakses sekarang maupun di masa depan. Praktik pengarsipan yang baik tidak hanya sebatas penyimpanan fisik, tetapi juga memastikan dokumen disusun secara sistematis, diberi label, dan dilindungi dari kerusakan atau kehilangan. Pengarsipan yang efektif meliputi pendokumentasian metadata, pengindeksan, dan teknik preservasi untuk menjaga bahan fisik maupun digital. Aksesibilitas juga harus seimbang dengan kerahasiaan, melindungi informasi sensitif sekaligus memungkinkan akses publik ketika tepat. Lebih dari sekadar tugas teknis, pengarsipan merupakan tanggung jawab etis: ia melestarikan ingatan kolektif, mendukung transparansi, dan memastikan pengetahuan serta sejarah tidak hilang, melainkan tetap berharga bagi generasi mendatang. Prinsip penting lain yang sering terabaikan adalah memastikan arsip disimpan dengan persetujuan para korban, termasuk persetujuan mengenai apakah bahan mereka dapat diakses publik, misalnya untuk digunakan dalam program negara seperti rekomendasi Tim PPHAM.
Tantangan pelestarian jangka panjang
Ada beberapa alasan mengapa arsip 1965 yang dimiliki organisasi-organisasi ini berada dalam kondisi berantakan. Faktor pertama adalah kurangnya pemahaman tentang praktik pengarsipan terbaik. Ilmu arsip dan pengelolaan arsip masih bersifat marginal dan belum banyak berkembang di Indonesia. Pembelajaran tentang arsip sebagian besar masih terbatas di ruang kelas universitas, dan sedikit peluang untuk mempelajari keterampilan berharga ini yang sangat dibutuhkan oleh lembaga yang bekerja di bidang hak asasi manusia di Indonesia.
Faktor kedua adalah keterbatasan sumber daya. Pengarsipan yang tepat membutuhkan dana yang signifikan dan tenaga ahli. Arsip jangka panjang memerlukan infrastruktur dan sistem teknologi yang canggih, serta fasilitas penyimpanan fisik yang memadai. Saat ini, satu-satunya lembaga negara yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah Arsip Nasional dan, di tingkat daerah, Arsip Daerah.
Faktor ketiga, dan yang paling signifikan, adalah sensitivitas politik dari arsip 1965. Saat ini tidak ada akses terhadap bahan-bahan terkait 1965 yang disimpan di arsip nasional Indonesia. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut menunjukkan sedikit minat untuk menyimpan dan melestarikan bahan-bahan terkait 1965 yang dikumpulkan oleh penyintas dan organisasi hak asasi manusia.
Akibat dari kurangnya keterampilan, dana, dan dukungan ini sangat merugikan koleksi 1965. Banyak bahan yang dikumpulkan pada awal 2000-an telah hilang. Beberapa hilang karena tingginya kelembaban di Indonesia, yang merusak kertas secara permanen dan menghancurkan kaset lama, sehingga bahan-bahan tersebut membusuk di lemari. Bahan lain hilang akibat banjir, atau karena hilangnya hard drive komputer dan cadangan data yang tidak memadai. Dalam beberapa kasus, bahan-bahan ini sengaja dihancurkan karena dianggap terlalu berbahaya untuk disimpan.
Arsip penyintas
Tugas pelestarian arsip 1965 kini menjadi sangat mendesak. Transparansi dan akses terhadap arsip dimulai dengan pengakuan bahwa arsip adalah tanggung jawab bersama. Arsip bukanlah milik lembaga atau individu yang mengumpulkan atau menyimpannya—arsip merupakan sumber daya publik. Arsip mendukung akuntabilitas dengan memungkinkan korban, peneliti, dan advokat menghadapi impunitas dan mendorong tercapainya kebenaran. Lebih dari sekadar tempat penyimpanan bukti, arsip melestarikan ingatan kolektif dan memperkuat suara-suara yang terpinggirkan. Dengan demikian, arsip memainkan peran penting dalam pendidikan, advokasi, dan perlindungan hak asasi manusia, memastikan masa lalu menjadi pelajaran bagi masa depan.
Peran arsip dalam memajukan hak asasi manusia sangat signifikan di Indonesia, sebuah negara dengan sejarah kompleks pemerintahan otoriter, kekerasan politik, dan perjuangan berkelanjutan untuk keadilan. Arsip yang dikelola dengan baik dan sesuai prinsip pengarsipan berbasis HAM memiliki potensi untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM berat di masa lalu dan menghadirkan keadilan bagi korban. Indonesia memilih jalur “non-yudisial” untuk menangani sejarah pelanggaran HAM berat ini, tetapi rekomendasi Tim PPHAM menekankan perlunya pengumpulan dan pelestarian data terkait pelanggaran tersebut.
Dalam konteks genosida 1965, pengarsipan menghadirkan tantangan tersendiri. Selain fakta bahwa banyak korban (dan pelaku) telah meninggal atau sudah sangat tua, waktu yang tersisa untuk mengumpulkan data dari mereka yang dapat memberikan kesaksian langsung juga sangat terbatas. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh organisasi penyintas dan organisasi pendukung selama tiga dekade terakhir kini berada dalam kondisi terancam, dan banyak di antaranya telah hilang.
Dalam situasi inilah, pada tahun 2018, sekelompok peneliti Indonesia dan internasional membentuk Indonesia Trauma Testimony Project (ITTP). Tujuan utama ITTP adalah mengumpulkan, mendigitalkan, dan melestarikan arsip komunitas penyintas yang sangat terancam punah ini, bekerja sama dengan para pemegang arsip, untuk memastikan arsip tersebut menjadi catatan permanen kesaksian mata mengenai periode gelap dan menentukan dalam sejarah Indonesia. Pekerjaan proyek ini dimulai pada 2018 dengan merundingkan serangkaian protokol yang disepakati bersama kelompok penyintas, tetapi akibat penundaan karena pandemi COVID-19, proses digitalisasi arsip baru dimulai pada 2024. Kini, tengah berjalan di tengah proyek, dan didukung oleh berbagai lembaga nasional dan internasional untuk menjamin pelestarian dan pengarsipan yang tepat, ITTP berharap arsip yang dihasilkan akan melestarikan memori 1965 untuk saat ini dan masa depan.
Sri Lestari (Ayu) Wahyuningroem memimpin Pusat Studi Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Risetnya berfokus pada hak asasi manusia dan keadilan transisi.