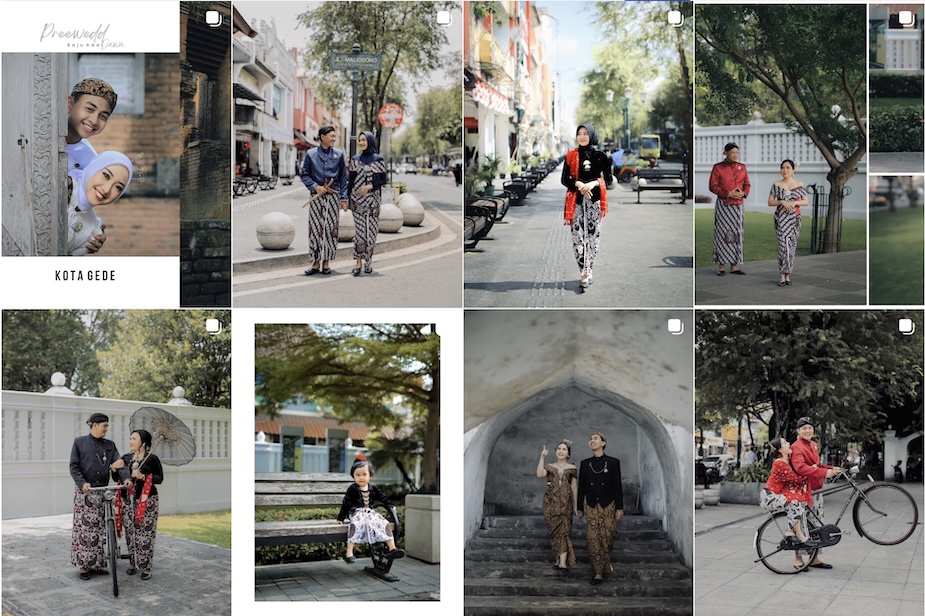Impunitas para pelaku masih merajalela, dan keheningan mengenai para pelaku, nasib para korban, serta konsekuensi sangat mencolok
Penyangkalan terhadap genosida yang terjadi di Indonesia setelah 1 Oktober 1965 memiliki dimensi kultural, hukum, diskursif, dan afektif. Genosida ini merupakan salah satu pembantaian massal terbesar setelah Perang Dunia Kedua, namun hampir tidak dikenal secara internasional. Di dalam negeri, impunitas para pelaku masih merajalela, dan keheningan mengenai para pelaku, nasib para korban, serta konsekuensi dari pelanggaran HAM berat ini sangat mencolok. Artikel ini berfokus pada dua dimensi dari penolakan ini: penyangkalan antisipatif, yang berkaitan dengan konstruksi narasi Gerakan 30 September, dan penyangkalan epistemik, yang merujuk pada bagaimana pembantaian dan konteksnya ditafsirkan serta diputarbalikkan. Artikel ini diakhiri dengan merujuk pada konsep ‘infrastruktur impunitas’ dari Elizabeth Drexler yang merupakan konsekuensi dari penyangkalan genosida di Indonesia.
Penyangkalan antisipatif
Penyangkalan antisipatif mengacu pada bagaimana narasi tentang ‘kudeta komunis’ ditanamkan sejak awal dalam konstruksi Gerakan 30 September, di mana Jenderal Suharto memainkan peran kunci. Seperti yang dicatat oleh Jess Melvin dalam bukunya The Army and the Indonesian Genocide: The Mechanics of Mass Murder, Suharto telah mengklaim bahwa gerakan tersebut adalah ‘kudeta komunis yang gagal’ bahkan sebelum nasib para jenderal yang diculik diketahui atau dewan revolusioner diumumkan. Dia telah menginstruksikan para komandan militer, terutama di Aceh, untuk menangkap dan membunuh para pimpinan PKI. Namun, ada lebih dari itu.
Respons dini ini menunjukkan adanya pengetahuan sebelumnya. Bukti lebih lanjut mengimplikasikan keterlibatan Suharto dalam perencanaan. Kolonel Latief dan Kolonel Untung—pemimpin Gerakan 30 September yang menculik para jenderal—keduanya telah mengunjungi Suharto beberapa bulan sebelumnya. Menurut Greg Poulgrain dalam JFK vs. Allen Dulles: Battleground Indonesia, keduanya melihat Suharto sebagai rekan seperjuangan, karena pernah bekerja sama dalam perang melawan Belanda di sekitar Yogyakarta pada 1948–1949. Koordinator operasi ini, Sjam (Kamaruzaman), ketua Biro Khusus PKI, juga memiliki hubungan lama dengan Suharto sejak perjuangan anti-Belanda pada akhir 1940-an.
Ali Murtopo, kepala intelijen Suharto, juga memiliki hubungan dekat dengan Sjam. Poulgrain menyatakan bahwa Murtopo mengatur agar preman-preman berpakaian sipil mendampingi truk-truk militer yang menjemput para jenderal pada 30 September. Preman-preman ini diduga terlibat dalam pembunuhan Jenderal Ahmad Yani. Di kediaman Jenderal Nasution, individu bersenjata yang tidak dikenal dari kalangan pengawal istana yang terlatih mencoba mengejar Nasution setelah dia melarikan diri. Kehadiran para aktor misterius ini kemungkinan berkontribusi pada kegagalan misi, karena para jenderal tidak pernah dibawa ke hadapan Presiden Sukarno—yang diduga merupakan rencana awal Gerakan 30 September.
Lebih jauh, Letnan Dul Arif—yang bertanggung jawab atas truk-truk dalam operasi penjemputan para jenderal—memberi tahu para prajurit bahwa jenderal-jenderal tersebut harus dibawa ‘hidup atau mati’, bertentangan dengan rencana untuk tetap menjaga mereka tetap hidup. Untung dan Latief menyangkal pernah mengeluarkan perintah tersebut. Poulgrain mengindikasikan bahwa orang lain, kemungkinan besar Murtopo (yang pernah menjadi atasan Dul Arif pada 1950-an), memberikan perintah fatal itu. Setelah Suharto mengambil alih pimpinan TNI, Dul Arif melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh Murtopo di dekat Brebes, Jawa Tengah. Dia kemudian menghilang, membungkam seorang saksi kunci.
Dalam historiografi peristiwa 1965 yang muncul kemudian, Suharto menempatkan dirinya sebagai pahlawan yang menyelamatkan bangsa dari kejahatan komunis. Tim intelijennya menyebarkan narasi tentang keberanian dan keadilannya, menggambarkan komunis sebagai pembunuh kejam. Meski masih banyak pertanyaan tak terjawab, bukti yang ada menunjukkan keterlibatan Suharto. Namun, belum pernah ada penyelidikan menyeluruh.
Penyangkalan epistemik
Penyangkalan epistemik atau interpretatif merujuk pada bagaimana PKI dan organisasi massanya digambarkan sebagai amoral, hiperseksual, anti-agama, dan anti-Pancasila. Kampanye fitnah dan distorsi ini menanamkan rasa takut dan kepatuhan.
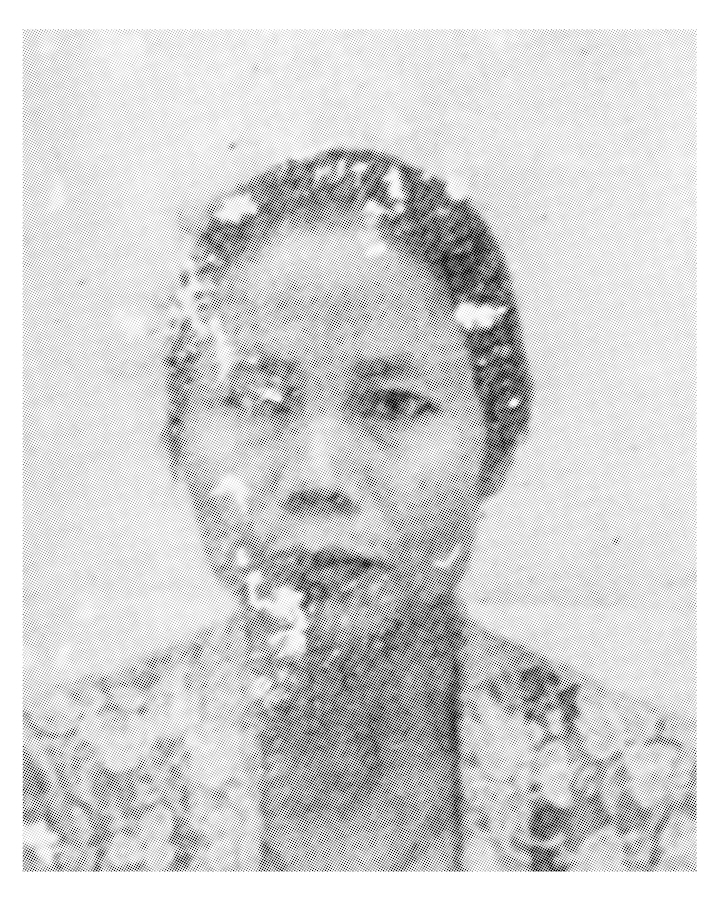
Salah satu contoh utama adalah fitnah seksual terhadap Gerwani, organisasi perempuan terbesar ketiga di dunia saat itu. Para gadis muda dituduh menari erotis di lokasi eksekusi, menggoda para jenderal yang masih hidup, dan memotong alat kelamin mereka. Cerita-cerita ini, yang disebarluaskan oleh media negara, sepenuhnya salah tetapi efektif dalam menghasut kekerasan. Hingga kini, label ‘Gerwani baru’ masih digunakan sebagai hinaan untuk membungkam aktivisme perempuan dengan mengaitkannya pada penyimpangan seksual.
Rezim juga menulis ulang peristiwa-peristiwa sejarah penting lainnya untuk menggambarkan PKI sebagai pengkhianat bangsa. Pemberontakan 1926–1927 oleh anggota PKI dan pemimpin Muslim progresif digambarkan secara keliru sebagai plot komunis yang memanipulasi umat Islam. Padahal, tokoh-tokoh Islam pro-komunis seperti Haji Misbach dan Haji Datuk Batuah telah mengembangkan bentuk Islam progresif yang sejalan dengan nilai-nilai sosialisme.
Demikian pula, Pemberontakan Madiun 1948 digambarkan sebagai pengkhianatan komunis terhadap negara, meski sebenarnya berakar pada ketegangan Perang Dingin dan upaya Wapres Hatta untuk merestrukturisasi militer. Meskipun mayoritas korban adalah anggota kelompok sosialis, peristiwa ini digambarkan sebagai pengkhianatan terhadap umat Islam. Sementara itu, pemberontakan Darul Islam—yang jauh lebih brutal dan berlangsung lebih lama—justru diminimalkan dalam buku-buku sejarah, meski telah mendeklarasikan negara Islam dan menewaskan sekitar 20.000 orang, mayoritas Muslim.
Peristiwa lain yang didistorsi melibatkan ‘aksi sepihak’ pasca undang-undang reforma agraria 1959. Hukum ini bertujuan meredistribusi tanah dari tuan tanah besar—termasuk kyai kaya dan militer—kepada petani tak bertanah. Karena ada perlawanan dari kyai kaya, implementasinya tersendat. Sejak 1963, petani miskin mulai menduduki tanah dengan dukungan serikat tani, seniman progresif, dan Gerwani. Di Jawa Timur, hal ini memicu bentrokan dengan pemuda Nahdlatul Ulama dan penangkapan ratusan petani, meski korban jiwa sebenarnya minim. Namun, aksi-aksi ini dibingkai sebagai serangan komunis terhadap Islam dan digunakan untuk membenarkan pembantaian pasca-1965.
Dengan demikian, penyangkalan atas keterlibatan militer dalam genosida bergantung pada kebohongan terang-terangan, penebaran ketakutan, dan distorsi sejarah. Skala penuh pembunuhan dan pemenjaraan korban di kamp kerja paksa tidak pernah diungkapkan. Para korban diubah menjadi kriminal, bersalah hanya karena menjadi anggota partai yang amoral—padahal PKI baru dinyatakan ilegal pada Maret 1966. Pembalikan kesalahan ini, ditambah dengan tidak adanya pertanggungjawaban, membentuk apa yang disebut oleh Elizabeth Drexler sebagai ‘infrastruktur impunitas.’ Melalui ketakutan, distorsi, dan propaganda, budaya kepatuhan diciptakan. Impunitas yang terus berlangsung membuat penyelidikan terhadap genosida menjadi berbahaya secara politik. Hal ini juga memungkinkan pelanggaran militer lanjutan di wilayah seperti Aceh, Timor Leste, dan Papua. Remiliterisasi Indonesia saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengatasi kejahatan masa lalu. Sebaliknya, hal ini justru memperkuat keheningan dan impunitas yang membuat para pelaku pelanggaran HAM berat lolos dari keadilan.
Saskia Wieringa adalah penulis beberapa buku tentang genosida 1965, termasuk Sexual Politics in Indonesia (2002) dan dengan Nursyahbani Katjasungkana Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined Evil (2019).