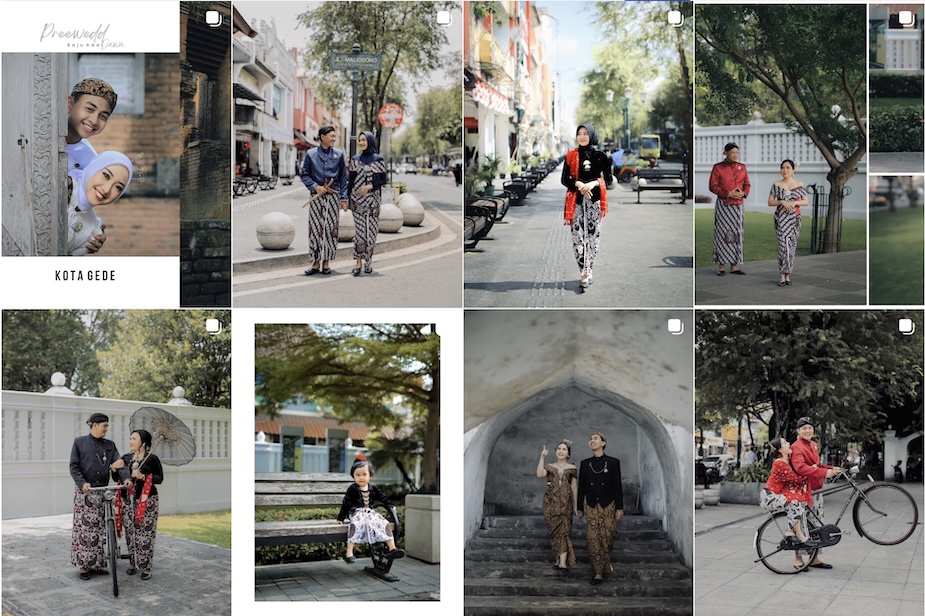Generasi muda dan pembunuhan massal 1965
Belakangan ini, publik Indonesia diramaikan oleh rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah Nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan proyek ini bertujuan untuk menghapus bias kolonial dan menyajikan sejarah dalam nada positif. Tentu saja rencana ini menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Pasalnya, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia saat ini memiliki keterikatan dengan Orde Baru dan bahkan diduga terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM, mulai dari Timor Timur hingga kerusuhan massal dan kekerasan anti-Tiongkok pada Mei 1998. Banyak yang khawatir proyek ini digunakan untuk menghapus jejak keterlibatan elite politik dalam sejarah kelam bangsa.
Gonjang-ganjing revisi sejarah nasional ini muncul hampir bertepatan dengan waktu saya bergabung ke dalam tim Indonesia Trauma Testimony Project (ITTP). Saya diajak masuk untuk membantu mengumpulkan kesaksian, dokumen, dan peninggalan lain terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM pasca pembunuhan massal 1965-1966, sebuah peristiwa yang masih sangat sensitif di Indonesia hingga saat ini. Saat saya mendengar isu penulisan ulang sejarah dan diskursus mengenai penulisan Peristiwa Mei 1998, ada satu hal yang muncul dibenak saya, ‘Kalau Peristiwa 98 aja kayak gini, gimana lagi 65?’
Pentingnya merawat ingatan 1965
Tahun ini, kita sudah akan memperingati 60 tahun terjadinya pembunuhan massal 1965. Akan tetapi, hingga saat ini masih belum ada hilal penyelesaian akan kasus HAM berat ini maupun juga rekonsiliasi nasional yang telah berulang kali dijanjikan pemerintah sejak 1998.
Di saat pemerintah tidak bisa memberikan kepastian, para penyintas juga satu persatu mulai dimakan usia. Saat ini, saya sedang rutin untuk mengunjungi para penyintas ditemani oleh Mas Marsis dan Mbak Ayu, dua anak korban yang juga aktif dalam komunitas penyintas 65. Saat memilih penyintas yang akan saya dokumentasikan, kami pun harus berhati-hati sebab ada banyak penyintas yang sudah tidak bisa menceritakan kisahnya dengan baik. Sebagian sudah kabur ingatannya, sebagian lagi sudah sulit diajak berkomunikasi.
Di saat yang sama, dokumen-dokumen, foto-foto, ataupun barang peninggalan lainnya juga tidak bernasib lebih baik. ‘Wah Mas, dulu sih ada, tapi sekarang gak tau ke mana,’ adalah respon yang sering saya dapatkan ketika saya bertanya soal barang dan dokumen peninggalan yang masih mereka miliki. Tidak terbayang, berapa banyak kisah tentang Kekerasan massal 1965 yang telah hilang ditelan zaman.
Sebelum ini, memang sudah banyak usaha-usaha untuk merawat ingatan mengenai pembunuhan massal 1965. Seperti yang dikatakan oleh Ken Setiawan, salah satu peneliti ITTP, bahwa sebenarnya sudah banyak arsip dan dokumentasi yang dikumpulkan, baik oleh para penyintas, LSM, ataupun para pelaku. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada upaya-upaya untuk mengoleksi, menyimpan, mendata, dan merawat arsip-arsip tersebut serta membukanya kepada publik.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Rangga, salah satu peneliti lapangan di ITTP. Menurutnya, ITTP menjadi penting karena proyek ini tidak hanya mengumpulkan arsip-arsip serta kesaksian para penyintas, tetapi juga membukanya untuk publik. Hilya, anggota ITTP lainnya, juga menyebutkan pentingnya keterbukaan akses ke arsip-arsip terkait pembunuhan massal 1965. Menurutnya, masih banyak orang yang belum mengetahui sejarah peristiwa tersebut, meskipun mereka berpendidikan tinggi, karena adanya upaya-upaya untuk menyembunyikan kisah-kisah tersebut.
Generasi muda
Proyek riset ITTP melibatkan 7 tim daerah untuk mengumpulkan arsip-arsip yang terancam punah dan melakukan wawancara dengan para penyintas serta saksi mata genosida 1965. Tim ITTP daerah ini memiliki empat anggota peneliti lapangan. Saya sendiri adalah anggota yang paling baru bergabung dengan tim ini. Selain saya, ada Pipit yang adalah pengurus Kiprah Perempuan (Kipper), komunitas penyintas perempuan; Rangga, seorang fotografer dan anggota Mes 56, kelompok seniman muda; dan Hilya, anggota kelompok SEMAI yang selama ini aktif dengan para penyintas di wilayahnya.
Pada suatu kesempatan, kami berkumpul untuk ngobrol bareng, saling bertukar cerita pribadi maupun pengalaman saat turun lapangan. Saat kami bercerita mengenai mengapa kami akhirnya ‘terjerumus’ ke isu 1965, saya pun mendengar banyak kisah yang menarik.
Saya kenal dengan Pipit cukup lama. Kami pertama kali bertemu saat saya mengantar ibu saya ke pertemuan Kipper. Sejak saat itu, kami sering bertemu di berbagai acara. Saya cukup kaget saat ia bercerita bagaimana ia sempat mengalami masa-masa sulit untuk menerima saat kedua orangtuanya memberitahu kalau mereka adalah mantan tapol.
Menurut kisahnya, saat masih sekolah, ia masih mengalami masa di mana para siswa diwajibkan untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI yang membuatnya melihat PKI (Partai Komunis Indonesia) sebagai ‘kelompok yang jahat.’ Saat itu, ia masih belum tahu kalau kedua orang tuanya adalah mantan tapol. Saat SMA, barulah bapak dan ibunya bercerita kalau mereka adalah bagian dari ‘orang-orang yang jahat’ itu. Ia pun sempat membuatnya kurang percaya diri, menarik diri dari lingkungan, dan tidak mau berterus terang tentang siapa keluarganya.
Barulah saat masuk kuliah, ia bertemu dengan teman-teman yang mengajaknya berdiskusi mengenai isu 65, meskipun mereka bukanlah dari keluarga penyintas. Setelah itu, ia pun mulai bertemu dengan anak-anak penyintas lainnya yang kemudian bersama membentuk Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham). Sejak saat itu, ia perlahan-lahan aktif di dalam isu ini hingga sekarang.

Sama seperti saya dan Pipit, Rangga juga berasal dari keluarga penyintas. Awalnya, ia merasa penasaran dengan lokasi makam kakeknya. Setiap ia bertanya ke ayahnya, ia selalu mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Baru pada tahun 1998, setelah Suharto jatuh, orangtuanya bercerita kalau kakeknya dari pihak ayah hilang, sementara kakek dan neneknya dari pihak ibu ditahan karena kasus 65. Namun, cerita orangtuanya tidak serta merta membuatnya langsung aktif dalam isu 65.
Rangga bercerita sekitar tahun 2000-an, ia sebenarnya sudah mulai sedikit demi sedikit ‘berkenalan’ dengan isu 1965. Ia ikut mengunjungi Luweng Grubug. Sebuah goa di Gunung Kidul di mana menurut cerita orang banyak orang yang diduga terlibat dengan PKI ataupun organisasi underbouw-nya dieksekusi, salah satunya ialah kakeknya. Setelah itu, Rangga juga mulai menemani ibunya untuk menemui beberapa korban. Rangga baru benar-benar tertarik untuk bekerja dengan isu 1965 pada tahun 2013. Saat itu, sebuah acara yang dihadiri oleh beberapa penyintas diserbu oleh sekelompok ormas. Kasus tersebut membuatnya berpikir bahwa tidak masuk akal kalau pada tahun tersebut, lama setelah Peristiwa 65 terjadi, masih ada penyerangan terhadap penyintas, apa lagi yang hadir saat itu kebanyakan adalah lansia. Dari situ, ia mulai melakukan riset kecil-kecilan tentang 1965, mengobrol dengan beberapa kawan, untuk mencari jawaban sebuah pertanyaan, mengapa kakekku dihilangkan?
Berbeda dengan Rangga dan Pipit, Hilya tidak datang dari keluarga penyintas. Keaktifannya di isu 1965 bermulai saat ia memasuki masa akhir kuliah. Karena memiliki waktu luang, ia pun bergabung dengan beberapa teman dari berbagai kampus untuk belajar tulis-menulis di sebuah kafe. Ternyata, sang pemilik kafe adalah seorang penyintas. Darinya Hilya mulai sedikit-demi sedikit berkenalan dengan isu ini. Dia baru benar-benar tertarik untuk mendalami isu 1965 saat hadir dalam takziah untuk salah satu penyintas yang meninggal. Dari situ, ia mulai bertemu dengan beberapa orang yang aktif di isu ini. Ia dan kawan-kawannya lalu aktif mencari tahu orang-orang yang aktif di isu 1965, yang kemudian membuatnya bertemu dengan para penyintas.
Saat kami mengobrol, saya bertanya kepada Hilya, kenapa sih tertarik dengan isu 1965, padahal ia tidak punya ikatan dengan genosida 1965. Katanya, yang membuatnya tertarik dengan pembunuhan massal 1965 adalah kedekatannya dengan isu perempuan. Saat itu, ia juga sedang belajar isu feminisme, dan ia melihat bagaimana pelanggaran HAM massal memiliki ikatan yang kuat dengan sejarah gerakan perempuan di Indonesia.
Kisah dari lapangan
Turun ke lapangan dan bertemu korban selalu membawa pelajaran baru. Salah satu hal yang membuat kaget adalah bagaimana trauma dan ketakutan masih membekas, bahkan setelah 60 tahun berlalu. Saya masih menemukan penyintas yang meminta untuk disamarkan, ataupun yang tidak berani untuk menceritakan latar belakangnya, mengapa ia ditahan pasca 1965.
Trauma ini juga dialami oleh generasi kedua (anak korban). Hilya bercerita tentang anak penyintas yang mendapatkan surat kaleng dan tidak bisa bersekolah di sekolah negeri. Ia juga menemukan ada generasi ketiga dan keempat yang masih tidak bisa mendaftar menjadi anggota polisi karena masih memiliki hubungan keluarga dengan mantan tapol. Ia juga masih bertemu dengan penyintas yang menyembunyikan latar belakangnya sebagai anggota Gerwani, sehingga ia harus menemui penyintas tersebut berulang kali untuk membangun kepercayaan dengan mereka.
Mendengarkan kisah para penyintas juga menjadi suatu tantangan tersendiri secara emosional. Pipit bercerita betapa terenyuhnya ia ketika mendengarkan salah seorang mantan guru hanya meminta satu hal supaya harga dirinya dikembalikan. Ia pernah ditangkap oleh mantan muridnya sendiri, dipukuli, diarak, dan disiksa saat di dalam tahanan. Ia berada di dalam tahanan untuk waktu yang lama, tetapi pengalamannya tersebut membuatnya merasa kehilangan harga diri.
Sementara itu, Rangga lebih fokus pada arsip. Ia menemukan berbagai dokumen berasal dari para pelaku yang membuktikan keterlibatan mereka dalam Pembunuhan Massal 1965. Selama di lapangan, ia telah menemukan berbagai arsip menarik. Salah satunya adalah daftar warga yang tersangkut G30S di desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia juga menemukan kartu-kartu anggota, lengkap dengan fotonya. Menurutnya, penemuan arsip-arsip penting tersebut adalah sebuah pencapaian yang menyenangkan untuknya.
Selain itu, ia juga belajar banyak hal dari arsip-arsip tersebut. Contohnya, ia dapat mengetahui bagaimana kebanyakan korban dan tapol adalah kelas pekerja, seperti buruh dan petani. Ia juga menemukan bagaimana sebagian besar dari para tapol berusia 40-an tahun, yang mana adalah masa-masa produktif seseorang. Ia menduga ini adalah penyebab bagaimana sebagian besar keluarga penyintas mengalami kesulitan ekonomi.
Akan tetapi, juga ada banyak kisah menyenangkan yang kami alami selama di lapangan. Seperti yang Pipit alami ketika ia berkunjung ke salah satu penyintas, ia diajak ke kebun untuk panen singkong untuk dimakan bersama. Hal-hal kecil tetapi hangat seperti ini sering terjadi ketika kami berkunjung ke para penyintas, yang membuat kami merasa diterima dengan baik seperti keluarga, yang membuat kami senang dan bersemangat untuk bertemu dengan mereka dan membantu menyuarakan kisah-kisah mereka kepada masyarakat luas.
Bimo Bagas Basworo adalah seorang penulis konten dan anggota tim peneliti ITTP. Lulusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta yang tertarik dengan isu-isu sosial dan hak asasi manusia.