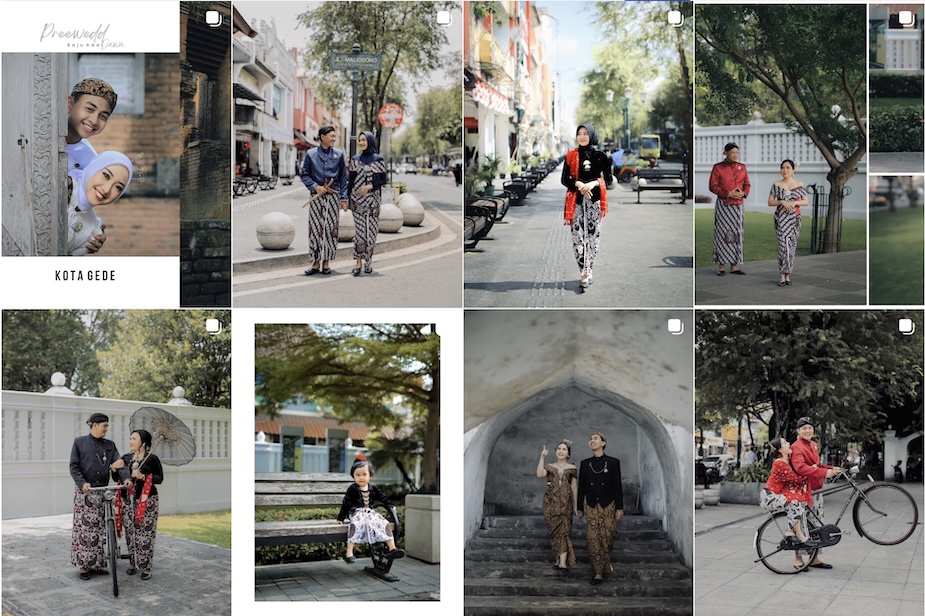Kisah penyintas 1965 di Sumatera Utara
Tulisan ini merupakan ulasan singkat tentang tiga orang penyintas peristiwa 1965 di wilayah Sumatera Utara. Mereka saling terpisah, akan tetapi mengalami peristiwa yang sama yakni menjadi korban kerja paksa dan penempatan di tempat penahanan umum (TPU). Mereka para penyintas yang berumur 88 tahun, ada yang berumur 70 tahun dan ada yang berumur 84 tahun. Ketiga penyintas tersebut mengalami kisah pahit dan menyedihkan yakni kerja paksa dan penempatan di TPU pada rentan waktu 1966-1975.
Pasca terjadinya peristiwa 1965, mereka mendabatkan lebelisasi dan cap yang begitu dilekatkan pada mereka dan keluarganya. Itu yang kemudian memaksa mereka harus patuh pada apa yang diperintahkan oleh Tentara. Lebelisasi dan cap keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kemudian memaksa mereka wajib lapor, ditahan juga dipekerja paksakan. Penahanan dan pelaporan yang diwajibkan kepada para penyintas ini kala itu, menurut penulis untuk mengakumulasi jumlah mereka karena akan ditransaksikan kepada perusahaan dan pemborong (pribadi) yang membutuhkan jasa.
Kerja paksa
Nomenklatur kerja paksa memang tidak asing di telinga kita. Kerja paksa terjadi pada masa penjajahan dan saat peperangan. Di Indonesia banyak pembangunan jalan dan gadung dibangun oleh mereka yang dipekerja paksakan oleh penjajah. Tentu kerja paksa bersifat memaksakan kehendak yang mempekerjakannya.
Pasca peristiwa tahun 1965, banyak penyintas 1965 yang mengalami kerja paksa. Kisah salah satu penyintas di Sumatera misalnya ia dipekerja paksakan untuk membuka lahan perkebunan di wilayah Sumatera Utara. Ia pernah dibawa ke salah satu kabupaten untuk membuka hutan yang akan dijadikan perkebunan. Tentu iya terpaksa melakukan karena dibawah kendali dan pengamanan militer saat itu. Begitu juga dengan penyintas lainnya, pernah bekerja di perkebunan dengan kontrak kerja paksa, di PT P____ selama 5 tahun. Di borong oleh A____, K_____ dan B____ kurang lebih selama 20 tahun. Ada juga penyintas lain yang dipekerja paksakan untuk pembangunan jalan di salah satu Kota Besar di Sumatera Utara dan wilayah lainnya serta mencetak sawah di salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara.
Menurut mereka para penyintas, yang mengalami kerja paksa dengan terlebih dahulu dipanggil oleh dan melalui kepala Desa, kemudian di awasi secara ketat oleh tentara, jika yang dikerjakan seperti cetak sawah atau menanam hasilnya dapat dibawa pulang. Jika penyintas tersebut akan pulang, maka harus menunggu waktu sampai 6 bulan satu kali.
Saat penyintas ikut kerja paksa, tentara kemudian mempersempit lahan pekarangan rumah dan perkebunan yang mereka miliki. Pola yang dibangun oleh tentara melalui Kepala Desa adalah pengumpulan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KRPT) yang telah dikumpulkan sebelum maupun saat peristiwa 1965. Dalih pengumpulan itu adalah pembaharuan dokumen kepemilikan tanah. Akan tetapi karena dibawah ancaman militer, ternyata dokumen tersebut diserahkan ke Perkebunan, yang oleh Perkebunan dibakar/ dimusnahkan.
Ketika gejolak berlangsung, ada sebahagian penyintas mempertahankan pekarang rumah dan perkebunannya. Tentara kala itu bertanya soal KRPT, yang jika tidak bisa dibuktikan akan digusur paksa. Pola ini menurut penulis sendiri adalah sistematika perampasan hak properti secara paksa, mereka saat mengalami kekerasan dan dipekerjapaksakan, saat yang sama kehilangan tanah yang diwariskan oleh keluarganya.
Tempat Penahanan Umum (TPU)
Secara pribadi saat mendengar TPU saya merasa sangat asing. Yang kemudian para penyintas mengartikannya sebagai lokasi hutan belantara yang sudah diukur dan ditetapkan oleh pemborong/ perusahaan untuk lahan yang akan dijadikan usaha perkebunan.

Salah satu penyintas menceritakan bahwa, TPU diawali dengan panggilan yang dilakukan atau disampaikan oleh tentara setempat, kemudian saat melaksanakan pekerjaan diawasi secara ketat oleh tentara maupun perusahaan. Makanan yang penyintas dapatkan dibatasi atau dalam kondisi tertentu dikurangi bahkan tidak diberikan sama sekali. Penyintas tersebut harus berada di lokasi 2-5 tahun.
Penyintas menceritakan saat berada di lokasi TPU menyaksikan ia harus memakan buah-buahan pepohonan atau binatang yang mereka dapatkan di lokasi TPU. Tanpa sepengatuan tentara maupun perkebunan, karena jika mereka mendapatkan penyintas makan tanpa sepengetahuannya, akan disiksa secara kejam. Penyintas tersebut juga dalam kesaksiannya melihat penyintas lainnya mengalami pesakitan tanpa bantuan, sehingga TPU selain lokasi kerja paksa juga menjadi tempat kuburan bagi penyintas yang meninggal akibat kelaparan dan mendapatkan penyiksaan oleh perusahaan dan tentara.
TPU diberlakukan oleh Militer antara tahun 1966–1975, sedangkan kerja paksa pasca 1975 juga masih terjadi walaupun tidak semasif kurun waktu sebelumnya. Sehingga luasan hasil pekerjaan yang dilakukan melalui pola TPU jauh lebih luas dibandingkan dengan kerja paksa. Peruntukan hasil TPU sangat erat kaitannya dengan lokasi penguasaan perkebunan sawit yang berada di wilayah Sumatera hari ini. Beberapa titik lokasi bahkan menjadi titik balik konflik lahan, dan sampai hari ini masih menjadi masalah yang tidak terselesaikan.
Warisan ketidakadilan
Saat mengakhiri wawancara dengan para penyintas tersebut, penulis kemudian menutupnya dengan pertanyaan ‘jadi menurut Bapak apa yang seharusnya dilakukan oleh Negara/ Pemerintah hari ini?’ Hampir semua penyintas menjawab bahwa dari apa yang mereka alami, lamanya, tindakannya, sampai pada trauma mendalam, sulit negara ini mengambil langkah yang adil dan mengembalikan kebenaran dari sejarah. Misal yang disampaikan penyintas yang telah tua renta yang saat sampai sekarang ini sedang berjuang mengembalikan hak atas tanahnya. Menyampaikan ‘yang tanah kami sedikit yang sidang diperjuangkan dan menjadi hak kami dulu saja tidak kembali dan diselesaikan, konon lagi yang lain’. Imbuhnya saat ditanya.
Pada sesi perjalanan dan di setiap kesunyian pikirku, ‘apakah butuh batas waktu dalam penyelesaian?’ Aku sendiri menjawabnya tidak, tetapi sejarah harus terungkap, diselesaikan secara adil dan diobati (rehabilitasi) nama dan pesakitan yang mereka alami, kembalikan hak-hak mereka yang hilang. Kapan? Jangan pikirkan waktunya, Jangan lelah menuliskan kisahnya, karena ada dan akan ada generasi mendatang yang akan lahir dan mendorong untuk menyelesaikannya secara bertahap untuk sejarah peradaban Indonesia. Aku terus berdoa, semoga tuhan memberi kesempatan untukku melihat, mendengar dan merasakan keadilan bagi semua penyintas peristiwa 1965 yang ada di seluruh dunia.
Quadi Azam adalah peneliti lapangan dari ITTP, dan kerja bersama IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) Sumatra Utara. Dulu, dia merupakan koordinator dari IPT65 Sumatera Utara.