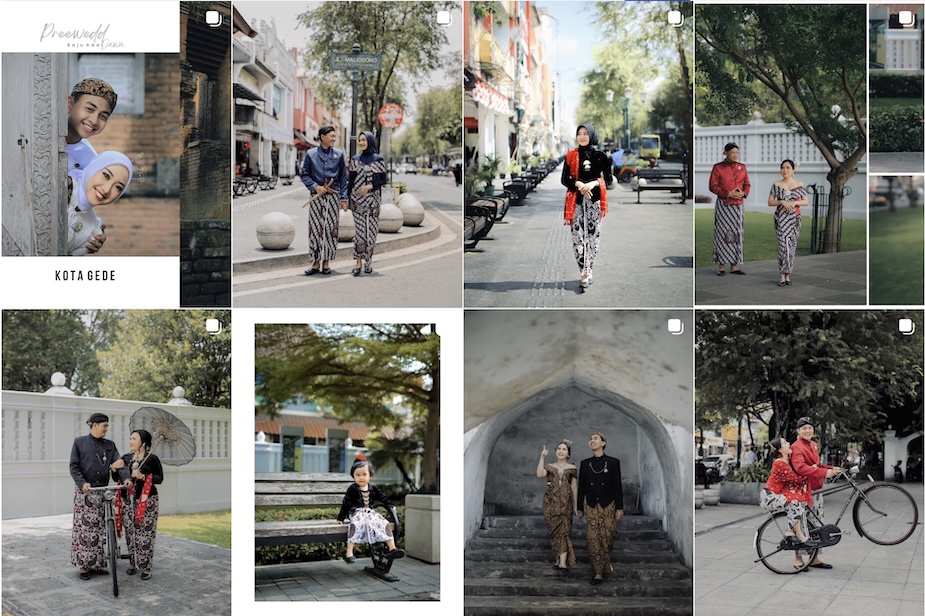Mengapa menolak tambang emas?
Wahyu Eka Styawan
Keberadaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur memiliki sejarah yang cukup panjang. Lahirnya pertambangan ini diceritakan dalam buku Ika Ningtyas, Dua sisi Tumpang Pitu: kilau emas dan kerusakan lingkungan (Tempo, 2019). Pada tahun 1995, PT Hakman Metalindo mendapatkan izin Kuasa Pertambangan (KP) untuk melakukan eksplorasi di wilayah seluas 62.586 hektar. Kawasan ini mencakup area konservasi penting, termasuk Taman Nasional Meru Betiri.
Saat itu PT Hakman Metalindo mengoperasikan tambang melalui tiga anak perusahaan yaitu PT Hakman Emas Metalindo (5.386 hektar), PT Hakman Platina Metalindo (25.930 hektar), dan PT Hakman Perak Metalindo (25.120 hektar). Perusahaan ini lalu mulai membuka jalan bagi eksploitasi tambang emas di sekitar wilayah Taman Nasional Meru Betiri, termasuk Gunung Tumpang Pitu. Namun, perjalanan Hakman Metalindo hanya seumur jagung. Tepat pada tahun 2006, Bupati Banyuwangi mengeluarkan keputusan berani dengan mencabut izin pertambangan tersebut, sehingga mengakhiri jalan mereka untuk mengusahakan lebih jauh pertambangan emas.
Pemerintah Banyuwangi kemudian mengalihkan izin tersebut kepada PT Indo Multi Cipta (IMC), yang berubah nama menjadi PT Indo Multi Niaga (IMN) pada tahun 2006. Setahun kemudian, PT IMN mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) seluas 11.621,45 hektar di Kecamatan Pesanggaran. Tetapi tak sampai melakukan eksplorasi, terjadi permasalahan di tubuh PT IMN, salah satunya karena kurangnya modal, sehingga proyek eksplorasi terhenti.
Kemudian, pada tahun 2012, PT IMN secara tidak terduga mengalihkan izinnya ke PT Bumi Suksesindo (BSI), anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MCG). Langkah ini memicu perselisihan dengan Intrepid Mines, sebuah perusahaan asal Australia yang sebelumnya menjadi mitra bisnis PT IMN. Intrepid merasa dicurangi dalam proses pengalihan izin tersebut. Konflik akhirnya berakhir setelah Intrepid menjual sahamnya kepada Kendall Court Resources Investments Ltd.
Pada tahun 2012 juga, secara kilat PT Bumi Suksesindo (BSI) memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seluas 4.998 hektar, yang berlaku hingga 25 Januari 2030. Sementara itu, PT MCG juga membentuk anak perusahaan bernama PT Damai Suksesindo (DSI) untuk melakukan eksploitasi di Gunung Tumpang Pitu, tetapi wilayahnya lebih luas karena mencakup Desa Sumberagung, Desa Kandangan dan Desa Sarongan. PT DSI kemudian mendapatkan IUP Eksplorasi seluas 6.623 hektar. Dengan demikian, PT Merdeka Copper Gold (MCG) menjadi pengendali utama tambang di Gunung Tumpang Pitu, didukung oleh jaringan investor nasional dan internasional. Keberadaan tambang ini semakin kokoh setelah dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banyuwangi 2012-2032, yang mengalokasikan 22.600 hektar untuk pertambangan di Kecamatan Pesanggaran dan Siliragung.

Tambang emas Tumpang Pitu telah melalui berbagai fase pergantian izin dan kepemilikan, dari tangan Hakman Metalindo hingga akhirnya dikuasai oleh PT Merdeka Copper Gold melalui anak perusahaannya, PT BSI dan PT DSI. Konsesi tambang ini terus mengalami ekspansi yang signifikan, dengan izin produksi yang masih berlaku hingga 2030. Perjalanan panjang perizinan ini mencerminkan bagaimana kepentingan industri pertambangan terus berkembang di wilayah ini, meskipun diiringi oleh berbagai konflik dan perubahan kebijakan yang menyangkut nasib sumber daya alam dan masyarakat sekitar.
Kronologi perlawanan
Cerita perlawanan terhadap tambang emas Tumpang Pitu hampir sepanjang cerita tambang sendiri. Di sini kita merujuk pada buku Ika Ningtyas yang lain, Menambang emas di tanah bencana (Resist Books, 2019). Babak pertama perlawanan berlangsung tahun 2007-2012, lalu babak kedua 2015-2018, dan ketiga tahun 2019-2023 - semuanya saling terhubung.
Babak pertama dimulai ketika warga mulai sadar mengenai dampak eksplorasi tambang terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka. Gerakan Masyarakat Anti Tambang (GERAMANG) mulai terbentuk secara informal, diinisiasi pada tahun 2007 oleh lima warga yang resah terhadap hadirnya PT Indo Multi Niaga (IMN). Meski belum memiliki pengalaman dalam mengorganisir aksi besar, mereka mulai melakukan protes terhadap truk-truk pengangkut alat berat perusahaan. Inisiatif ini menjadi langkah awal bagi lahirnya perlawanan yang lebih luas.
Pada babak kedua, yaitu memasuki periode 2015 hingga 2017, ketegangan semakin meningkat seiring dengan ekspansi tambang yang terus berlanjut. Pada 13 Oktober 2015, warga berhasil menghentikan puluhan truk pengangkut alat berat. Peristiwa ini memicu dukungan luas dari masyarakat sekitar. Tak lama setelah itu, pada 18 November 2015, lebih dari 3.000 warga turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi besar di depan kantor PT Bumi Suksesindo (BSI). Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar dalam sejarah sosial-politik Banyuwangi, membawa dampak besar terhadap masyarakat dan pemerintah setempat.



Tahun 2016 menjadi titik balik perjuangan. Sebuah posko perjuangan didirikan di Dusun Pancer, yang terletak di pesisir Desa Sumberagung. Posko ini menjadi pusat koordinasi aksi, namun juga menjadi awal dari kriminalisasi warga.
Meskipun protes masih berlangsung, PT BSI tetap memulai operasi penambangan emas pada 1 Desember 2016. Budi Pego dan tiga warga lainnya ditangkap dengan tuduhan menyebarkan komunisme, sebuah tuduhan yang kontroversial dan merupakan bagian dari upaya untuk membungkam perlawanan. Tepat pada April 2017, mereka berempat ditetapkan sebagai tersangka lalu dilepas sambil menunggu perkara. Budi Pego kembali ditangkap paksa. Setahun berselang ia divonis bersalah pada Januari 2018, meskipun kurang bukti. Vonis: 1 tahun penjara. Namun, saat melakukan kasasi di Mahkamah Agung (MA), hukuman Budi Pego ditambah menjadi 4 tahun penjara. Saat itu Budi Pego sudah lepas. Namun anehnya, setelah bebas, tidak ada penangkapan atau penahanan kembali pasca putusan kasasi MA.

Lalu, pada babak ketiga yakni 2019 hingga 2023, aksi simbolik menjadi strategi utama warga untuk menarik perhatian lebih luas. Pada tahun 2019, warga menggelar aksi ‘Kayuh Sepeda ke Surabaya’, menempuh ratusan kilometer demi menyampaikan protes langsung ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, represi terhadap gerakan semakin nyata. Saat aksi tersebut berlangsung, kantor LBH Surabaya yang memberikan pendampingan hukum bagi warga mengalami serangan oleh kelompok tidak dikenal.
Situasi semakin memanas pada 27 Maret 2020, saat warga protes dengan memblokade jalan ke arah lokasi pertambangan. Terjadi bentrokan besar antara warga tolak perluasan tambang dan aparat keamanan.
Perlawanan kembali berlangsung pada tahun 2022. Warga menolak ekspansi pertambangan menuju Gunung Salakan - salah satu gunung yang bertetangga dengan Gunung Tumpang Pitu. Penolakan tersebut dilakukan dengan menghadang pekerja perusahaan yang akan melakukan eksplorasi ke wilayah tersebut. Aksi juga dalam bentuk membuat tenda perjuangan dan solidaritas, sebagai ruang untuk bertemu dan sebagai tempat untuk mengawasi aktivitas perusahaan agar tidak masuk ke Gunung Salakan. Akhir Februari 2023 terjadi bentrok dengan aparat saat perusahaan mencoba masuk paksa Gunung Salakan.
Tak berselang lama, pada tanggal 24 Maret 2023, Budi Pego kembali ditangkap aparat keamanan. Kali ini ia kembali dimasukkan penjara dengan dalih menjalani sisa hukumannya yang kurang 3 tahun.

Perlawanan warga Tumpang Pitu berkembang dari aksi lokal menjadi gerakan besar yang mendapat dukungan luas. Meski kriminalisasi aktivis, represi aparat, dan tekanan perusahaan terus terjadi, perjuangan mereka belum berhenti. Konflik agraria di Dusun Pancer akibat pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih menjadi salah satu isu utama yang diperjuangkan. Ini menandakan bahwa perlawanan warga terhadap tambang Tumpang Pitu tetap hidup dan berlanjut hingga kini.
Dampak tambang
Penolakan terhadap tambang emas di Gunung Tumpang Pitu bukan sekadar reaksi spontan, melainkan cerminan dari kesedihan mendalam warga terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Warga di Desa Sumberagung, khususnya di Dusun Pancer, telah lama menyaksikan bagaimana eksploitasi tambang sedikit banyak telah mengubah kehidupan mereka. Apa yang dijanjikan sebagai pembangunan dan kesejahteraan justru berujung pada ancaman terhadap ekosistem, mata pencaharian, dan keadilan agraria.
Dahulu, Gunung Tumpang Pitu merupakan kawasan hutan lindung yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekologi di pesisir Banyuwangi. Namun, keberadaan tambang emas di wilayah ini telah menyebabkan penggundulan hutan dalam skala besar, menghilangkan daerah resapan air, serta meningkatkan risiko bencana seperti longsor dan banjir. Mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi petani perlahan mengering, sementara Sungai Katakan yang sebelumnya mengairi sawah warga kini ditanggul oleh perusahaan tambang, menyebabkan kesulitan air di Dusun Pancer. Bencana menjadi semakin akrab bagi warga yang tinggal di sekitar konsesi tambang emas Tumpang Pitu, mulai banjir beruntun dari tahun 2019-2021. Protes pada tahun 2019 dan 2020 salah satunya disebabkan oleh adanya banjir, selain juga karena jalan rusak.

Kemudian aktivitas tambang juga mengganggu warga sekitar. Salah satunya blasting. Tercatat pada tahun 2024 telah terjadi ledakan akibat aktivitas blasting. Pertama pada bulan Mei 2024, dampak dari blasting membuat getaran dan yang paling terasa di Pulau Merah. Efeknya, banyak wisatawan yang panik sehingga berhamburan untuk menyelamatkan diri. Lalu, peristiwa kedua pada bulan November 2024, dampak dari blasting membuat Gunung Tumpang Pitu runtuh dan longsoran itu langsung masuk ke laut. Peristiwa tersebut mengingatkan nelayan di Dusun Pancer pada kejadian banjir lumpur pada tahun 2016, di mana aktivitas pembukaan lahan tambang menyebabkan banjir bercampur lumpur dan masuk langsung ke laut.
Merusak ekonomi
Dampak ekonomis dari tambang emas Tumpang Pitu juga mulai dirasakan oleh warga Desa Sumberagung. Efek dari penambangan ini beriringan dengan merosotnya mata pencaharian warga. Mayoritas penduduk setempat bergantung pada pertanian dan perikanan, tetapi keduanya kini terancam akibat pencemaran dan alih fungsi lahan. Salah satu dampak yang dirasakan oleh warga adalah kondisi Sungai Katakan. Sungai yang selama ini menjadi sumber utama irigasi bagi petani, kini ditanggul oleh perusahaan tambang, menyebabkan banyak lahan pertanian kehilangan pasokan air. Sumur-sumur warga mulai mengering, terutama dalam dua tahun terakhir, membuat kehidupan semakin sulit.
Para warga yang berprofesi sebagai petani mulai mengeluhkan lahan pertanian yang dulu subur kini menyusut dan mengalami krisis air. Meski samar-samar disampaikan, tetapi isyarat itu tampak dari keluhan-keluhan mereka, terutama bagi petani buah naga. Desa ini dikenal produsen buah naga besar. Komoditas ini menjadi andalan warga Desa Sumberagung sejak 15 tahun terakhir. Selain buah naga juga ada komoditas jeruk. Para petaninya kini mengeluhkan tidak maksimalnya produksi buah mereka, terutama sejak kehadiran tambang. Salah satu yang mereka keluhkan tentunya terkait dengan akses air, dan potensi banjir saat musim hujan, terutama ketakutan mereka saat Sungai Katakan meluap.


Dampak yang lebih buruk lagi dialami oleh nelayan, yang mata pencahariannya bergantung pada laut. Mereka merasakan betul penurunan hasil tangkapan yang signifikan akibat pencemaran lingkungan dari limbah tambang. Kelompok nelayan di Dusun Pancer mengungkapkan, sejak tambang beroperasi, nelayan harus melaut sejauh lebih dari 5 mil pantai, dari sebelumnya hanya 1-3 mil pantai. Ikan pun banyak yang telah menghilang dari garis pantai karena rusaknya habitat mereka. Sebelum ada tambang, pada tahun 2010 total tangkapan ikan nelayan mencapai 10.280 ton, lalu menyusut sekitar 1/4-nya sejak banjir lumpur di tahun 2016, yang hanya menjadi 8.106 ton.

Kelompok lain yang ekonominya paling terdampak adalah sektor pariwisata. Dahulu Desa Sumberagung terkenal dengan wisata pantainya yang indah. Ombaknya lumayan besar, sehingga menjadi destinasi alternatif nelayan mancanegara yang jenuh dengan Pulau Bali. Tempat wisata itu bernama Pulau Merah. Bahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memasukkannya sebagai destinasi wisata utama dalam program Visit Banyuwangi, setara dengan Gunung Ijen.
Tetapi sejak kehadiran tambang, keberadaan Pulau Merah menjadi semakin sepi. Banyak resort yang gulung tikar. Wisatawan mancanegara mulai enggan datang. Meski masih dikunjungi wisatawan lokal, tetapi Pulau Merah sudah tidak seindah dahulu. Air laut kadang kala keruh. Pemandangan terganggu dengan hilangnya hutan lindung Tumpang Pitu oleh aktivitas tambang. Ditambah lagi aktivitas blasting tambang, menjadi penyebab merosotnya wisatawan ke Pulau Merah.
Petani yang produksi komoditasnya mengalami penurunan, lalu nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan dan sektor wisata yang mulai sepi. Pada akhirnya menjadi masalah bagi perekonomian lokal, tak sedikit dari mereka yang akhirnya terpaksa merantau atau terpaksa bekerja sebagai buruh outsourcing di pertambangan dan beberapa sebagai buruh harian lepas. Sebuah ironi, di mana mereka pada akhirnya dipaksa kehilangan kemandirian ekonomi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.



Tambang menggusur warga?
Tambang tidak hanya membawa dampak lingkungan, tetapi juga semakin memperburuk kondisi sosial warga. Misal, nasib buruk yang dialami oleh warga Dusun Pancer. Sebelum adanya konsesi tambang, mereka berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah, sebab selama ini mereka menempati tanah yang dikuasai oleh Perhutani. Dusun Pancer awalnya merupakan kawasan hutan lindung yang berbatasan langsung dengan laut.
Pada tahun 1994 terjadi gempa diikuti tsunami yang menimpa daerah Banyuwangi. Sebelum bencana tsunami, jumlah penduduk di Pancer relatif sedikit, hanya sekitar 1.000 jiwa. Tsunami menghancurkan sebagian besar permukiman yang ada. Setelahnya, pemerintah merelokasi warga ke wilayah yang lebih aman, dengan janji pemberian sertifikat tanah. Sayangnya, janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Warga tertinggal dalam ketidakpastian hukum atas tanah yang mereka tempati.
Selama satu dekade terakhir, status tanah di Pancer semakin kabur ketika Perhutani mulai mengklaim kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Beban pada warga tersebut semakin ditambah ketika konsesi tambang atas nama PT BSI dan PT DSI diterbitkan. Ini tentunya membuat warga berada dalam bayang-bayang penggusuran. Tanpa pernah dilibatkan dalam keputusan pemberian izin tambang, mereka merasa hak atas tanah yang mereka tinggali dirampas secara sepihak.
Ancaman terbesar bagi warga Pancer saat ini adalah penggusuran paksa. Dengan status tanah yang masih dianggap sebagai bagian dari kawasan Perhutani, dan tumpang tindih dengan konsesi pertambangan, warga tidak memiliki kepastian hukum atas rumah dan tanah mereka. Setiap saat, mereka bisa dipaksa keluar dari tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Dalam ketidakpastian ini, warga terus berjuang mempertahankan hak mereka atas tanah dan lingkungan yang semakin terancam oleh ekspansi industri tambang, yang didukung oleh kekuatan modal dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
Penolakan warga terhadap tambang di Tumpang Pitu bukanlah tanpa dasar. Sebab apa yang mereka lakukan hingga saat ini tidak kurang merupakan perjuangan untuk mempertahankan ruang hidupnya. Mereka sedang memperjuangkan hak alami yang melekat pada lingkungan, dan hak mereka atas mata pencaharian, demi keadilan agraria. Tambang bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan alat eksploitasi, yang merusak keseimbangan sosial dan ekologis yang telah lama dijaga oleh masyarakat setempat.
Wahyu Eka Styawan (Wahyuwalhijatim@walhi.or.id) bekerja dengan organisasi pembela lingkungan WALHI Jawa Timur.