Gerry van Klinken
Laporan Limits to Growth (‘Batas-Batas Pertumbuhan’) dari Proyek The Club of Rome pada tahun 1972 mengejutkan dunia dengan grafik ‘bisnis seperti biasa.’ Diproyeksikan: keruntuhan global pada suatu saat di abad ke-21. Kiamat! Ketidakmampuan atau penolakan untuk menghentikan konsumsi per kapita yang meningkat secara eksponensial menyebabkan polusi melonjak dan sumber daya anjlok hingga dunia tak lagi tertolong.
Tanda-tanda kenyataan mimpi buruk tersebut sebenarnya telah terlihat jelas di setiap lokasi tambang di seluruh dunia selama beberapa waktu. Tambang-tambang bermutu tinggi yang ‘gampang’ telah lama habis digali. Daripada berhenti untuk berpikir sehat sejenak, para penambang maju terus. Mereka buka tambang-tambang yang jauh lebih besar dan jauh lebih kotor di wilayah ‘frontier,’ yang umumnya pula dikelola secara buruk.
Hanya sedikit orang di belahan dunia Utara yang rupanya tertarik untuk menghentikannya. Mereka merasa ‘membutuhkan’ semua logam tersebut untuk mempertahankan gaya hidupnya. Terlebih lagi sekarang mereka harus mengurangi karbon dengan bantuan kincir angin dan mobil listrik yang kaya akan logam tanah jarang. Jadi, siapa yang bisa menghentikan perusakan tambang? Sepertinya perlawanan itu tergantung pada Ibu Bumi sendiri, dan pada manusia yang menamakan lokasi-lokasi tambang itu kampung halamannya. Buku Lian Sinclair bercerita tentang perlawanan yang dilakukan oleh manusia atas nama diri mereka sendiri, keturunan mereka, dan lingkungan mereka. Tiga studi kasus mendalam di Indonesia mengkaji apa yang telah mereka lakukan, bagaimana pihak yang memfasilitasi tambang meresponsnya, dan apa artinya ini semua bagi masa depan pertambangan di seluruh dunia.
Sebagian besar dari mereka adalah petani yang hidup secara subsisten. Sebagian adalah penambang skala kecil - yang kehadirannya menunjukkan kepada perusahaan tambang raksasa di mana letak bijih yang bagus. Banyak di antaranya adalah perempuan, yang tidak memiliki rasa takut, karena mereka telah melihat kerugian yang menimpa orang-orang yang mereka sayangi. Tidak ada yang duduk di dewan perusahaan; tidak ada yang duduk di parlemen atau kantor pemerintah; tidak ada yang memiliki tentara pribadi.
Ternyata cara-cara mereka cukup efektif. Tambang emas Kelian milik Rio Tinto di Kalimantan Timur pada saatnya termasuk di antara yang terbesar di dunia. Dengan bantuan militer Orde Baru Suharto, perusahaan ini mengusir 4.000 penambang skala kecil dan keluarga mereka dari daerah tersebut pada akhir 1980-an. Para penambang tradisional yang digusur dimukimkan kembali di hilir Sungai Kelian, di mana mereka ter-ekspos limbah tambang yang mengandung sianida di dalam air. Satu dekade kemudian, mereka tetap merasa ditipu karena tidak mendapatkan kompensasi secukupnya. Ketika Orde Baru runtuh di tengah protes rakyat pada tahun 1998, mereka mengambil kesempatan untuk berorganisasi. Mereka memblokade tambang selama dua bulan pada tahun 2000, yang mengakibatkan perusahaan kehilangan pendapatan sebesar US$12,5 juta. Ketika mereka membangun aliansi di luar lokasi tambang, protes mereka mendapat dukungan dari seluruh dunia.
Internasionalisasi serupa dari protes masyarakat di lokasi-lokasi ekstraktif lainnya - dari delta minyak Nigeria hingga Ok Tedi di Papua Nugini - mulai terjadi pada saat yang sama. Gejala ini memusatkan perhatian para eksekutif perusahaan pertambangan di seluruh dunia. Mereka khawatir akan kalah dalam sengketa peradilan hingga harus membayar kompensasi yang sangat besar. Jangan-jangan pemerintah di banyak negara berkembang akan mengatur apa yang dapat mereka lakukan di lokasi tambang mereka. Mereka mulai berbicara di depan umum tentang pentingnya mendapatkan ‘izin sosial untuk beroperasi.’ Perusahaan tambang Kelian termasuk yang pertama kali mulai bernegosiasi melalui mekanisme konsultatif yang lebih ‘partisipatif.’ Banyak dari mereka yang digusur akhirnya menerima paket kompensasi yang cukup besar sebagai bagian dari mekanisme baru ini.
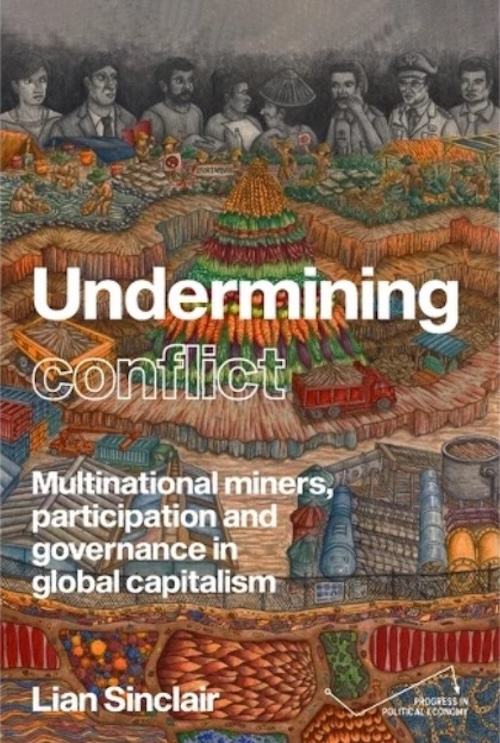
Tambang emas Gosowong di Halmahera Utara - studi kasus kedua dalam buku ini - sebagian dimiliki oleh perusahaan tambang Australia, Newcrest. Tambang ini mulai beroperasi pada tahun 1999, dan mengadopsi mekanisme ‘corporate social responsibility’ (CSR) yang sama seperti yang telah dirintis oleh Kelian dan yang lainnya. Di sini, tambang tidak perlu menggusur penduduk - tambang dibuka di hutan lindung yang jarang dihuni (setelah melakukan lobi untuk mengubah aturan lingkungan). Namun, penduduk setempat yang tinggal di hilir memprotes polusi air. Sianida memang ditemukan dalam air laut di muara sungai. Perusahaan telah belajar dari kesalahan pendahulunya. Daripada mendatangkan polisi, perusahaan menerapkan berbagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan. Perusahaan juga dengan cepat memberikan konsesi dalam menanggapi demonstrasi.
Masalahnya - Lian Sinclair menunjukkan hal ini dengan meyakinkan - mekanisme konsultatif ini tidak melakukan apa pun untuk mengatasi kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi penambang terhadap lingkungan sosial dan ekologi. Prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam berbagai pertemuan para eksekutif perusahaan tambang untuk ditindaklanjuti, tulisnya (hal. 50)
bersifat sukarela, tidak dapat ditegakkan lewat hukum, tidak jelas, berfokus pada proses, mengabaikan data yang dapat diukur, dan hanya memiliki sedikit persyaratan pelaporan atau pemantauan yang independen, sehingga memungkinkan fleksibilitas yang besar bagi perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaannya.
Pemilik tambang Gosowong tidak pernah merasa perlu untuk mengumumkan hasil pemantauan lingkungan mereka kepada publik - studi sianida yang dikutip di atas dilakukan oleh akademisi independen dari luar. Mekanisme pengaduan yang dijalankan oleh perusahaan ini dan perusahaan serupa hanya menangani masalah-masalah individual. Tetapi, (hal. 52):
meskipun proses pengaduan menghasilkan data ilmiah yang menarik, kerangka kerja teknokratis berarti bahwa dimensi sosial, politik, dan etika dari konflik diabaikan. Namun demikian, data yang dihasilkan melalui investigasi keluhan dapat digunakan oleh para aktor di tempat lain untuk kebutuhan partisipasi politik.
Satu-satunya hal yang berhasil, menurut Sinclair, adalah aksi militan dan langsung dari masyarakat setempat, di mana orang tersebut juga memiliki akses ke lahan subsisten mereka sendiri. Dalam kasus Gosowong, hal tersebut berupa demonstrasi berulang kali yang dipimpin oleh pemimpin adat, seorang perempuan bernama Afrida, yang bertindak sepenuhnya di luar kerangka konsultatif yang dibentuk oleh perusahaan (meskipun kerangka tersebut didukung oleh program PBB UNDP-LEAD). Hal inilah yang membuat warga mendapatkan kompensasi mereka, bukan proses yang dilembagakan oleh perusahaan.
Contoh terbaik dari perlawanan yang berhasil dapat dilihat pada studi kasus ketiga. Ini menyangkut rencana penambangan pasir besi di Kulon Progo, di pantai yang menghadap ke Samudera Hindia di provinsi Yogyakarta. Konsorsium Indonesia yang mengajukan rencana tersebut dipimpin oleh dua keluarga kerajaan - Hamengku Buwono dan Paku Alam. Penambangan bukit pasir di belakang pantai tersebut akan menghasilkan dua juta ton konsentrat besi kasar per tahun selama 18,5 tahun - untuk dimurnikan di tempat lain di Indonesia.
Ada orang yang tinggal di sana. Mereka tidak kaya - mereka menanam cabai dan melon di pasir pantai yang agak kering. Mereka tidak punya relasi dengan pihak yang kuat, dan tidak memiliki sejarah pengorganisasian politik. Namun pada tahun 2007 mereka mulai membuat penghalang jalan, mengadakan pawai dan demonstrasi. Untuk melakukan hal ini, mereka harus mengatasi rasa penghormatan kultural yang mengakar kuat terhadap sultan, di mana sultan dianggap memiliki kualitas ilahi. Pada akhirnya, mereka menolak para bangsawan karena mereka percaya bahwa ‘sultan dan Paku Alam-lah yang pertama kali mengkhianati tradisi Jawa demi kapitalisme’ (hal. 154). Aksi-aksi langsung ini, sejauh ini, membuat para penambang terusir. Para petani melakukan hal ini tanpa bantuan internasional. Perusahaan menawarkan mekanisme CSR kepada mereka, tetapi mereka menolaknya.
John Bellamy Foster dkk dalam bukunya The ecological rift (2010) menyatakan bahwa para aktivis perkotaan ‘post-materialis’ di Utara yang kaya menipu diri apabila mengira bahwa merekalah satu-satunya penghalang bagi korporasi raksasa yang merusak. Foster justru menunjuk pada apa yang dia sebut sebagai ‘proletariat lingkungan’ (hal. 440). Proletariat ini muncul di mana pun sistem kapitalisme merusak lingkungan dan secara bersamaan merugikan orang yang tinggal dan bekerja di sana.
Penduduk di tempat-tempat ini, seperti halnya kaum proletar Marx, tidak akan rugi dengan perubahan radikal yang diperlukan untuk mencegah (atau beradaptasi dengan) bencana.
Bisa jadi, para petani Kulon Progo ini persis menyerupai proletariat lingkungan sejenis. Bisa jadi, pada akhirnya mereka akan lebih berjasa untuk menyelamatkan planet ini daripada orang lain. Mereka melakukannya untuk kita, seperti halnya untuk diri mereka sendiri. Salah satu dari mereka mengatakannya dengan tepat (hal.153):
Manusia harus menjaga lingkungan dan kemudian lingkungan akan menjaga mereka, melindungi kehidupan mereka. Ini seperti hubungan timbal balik. Jadi, mereka mengerti: jika seseorang ingin mengambil tanah atau membangun sesuatu atau mengubah fungsinya, itu akan menghancurkan segalanya.
Lian Sinclair (diterj Nidya Paramita). 2024. Di bawah tanah: melawan pertambangan multinasional di Indonesia. Yogyakarta: INSISTPress.
Gerry van Klinken (gvanklinken@gmail.com) adalah anggota redaksi Inside Indonesia. Ia tinggal di Brisbane.












